File ini diproteksi
PERILAKU ORGANISASI DAN KEPEMIMPINAN
1. KEPEMIMPINAN
Pada dasarnya, setiap orang adalah pemimpin. Sekurang-kurangnya ia menjadi pemimpin atas dirinya sendiri. Konsekuensi kepemimpinan adalah pertanggungjawaban, sesuai dengan sistem dan mekanisme yang telah ditetapkan.
Kepemimpinan adalah pencerminan pola pikir, sikap, dan tindak sebagai hasil keterpaduan nilai, norma, ilmu, seni, watak, dan keperibadian. Sehingga dalam bentuk penampilan dan perilaku karakteristiknya sangat bervariasi:
1. Egoistik,
2. Paternalistik,
3. Materialistik,
4. Kharismatik,
5. Demokratik,
6. Universalistik,
7. Altruistik,
8. Profetik.
Kepemimpinan adalah suatu peran dan proses untuk mempengaruhi, menggerakkan, dan mengarahkan orang lain, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan suatu cara yang tidak memaksa. Sehingga orang bekerja dengan kesadaran, motivasi, etos, etik, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan (perundangan, prinsip, metoda, job-description, individual, team work).
Pemimpin adalah anggota dari suatu perkumpulan yang diberi kedudukan tertentu dan bertindak sesuai dengan kedudukannya. Seorang pemimpin adalah juga seorang ahli dalam perkumpulan yang diharapkan menggunakan pengaruhnya dalam mewujudkan dan mencapai tujuan kelompok. Pemimpin yang sebenarnya ialah seorang yang memimpin dan bukan seorang yang menggunakan kedudukannya untuk memimpin. Karenanya, ia pun sekaligus sebagai pengawas dan pengikut.
Ada beberapa teori tentang kepemimpinan, diantaranya :
1. Ordway Tead (1935)
Kepemimpinan adalah aktifitas mempengaruhi orang- orang agar mau bekerja sama untuk mencapai beberapa tujuan yang mereka inginkan.
2. Refter (1941)
Kepemimpinan adalah sesuatu kemampuan untuk mengajak atau mengarahkan orang orang tanpa memakai pembawa atau kekuatan formal jabatan atau keadan luar .
3. G. L. Freeman atau E. K. Taylor (1950)
Kepemimpinan adalah kemampuan untuk menciptakan kegiatan kelompok mencapai tujuan organisasi sehingga efektifitas maksimum dan kerjasama dari tiap-tiap individu.
4. Ralp M. Stogdill
Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan- kegiatan sekelompok orang yang terorganisir dalam usaha mereka menepatkan tujuan dan mencapainya
5. Franklyn S. Haiman (1951)
Kepemimpinan adalah suatu usaha untuk mengarahkan prilaku orang lain guna mencapai tujuan khusus.
6. Dubin (1951)
Kepemimpinan adalah menggunakan wewenang dan membuat keputusan- keputusan
7. Fred E. Tiedler (1967)
Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas kelompok untuk menentukan tujuan dan mencapainya.
8. Harold Koontz dan Cyrill O. Ddonnell (1976)
Kepemimpinan adalah seni membujuk bawahan untuk menyelesaikan pekerjaan- pekerjaan mereka dengan semangat keyakinan.
9. Keith Devis (1977)
Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mengajak orang lain untuk mencapai tujuan tertentu dengan penuh semangat.
10. Paul Hersey dan Kenneth H. Blanchard (1982)
Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan individu atau kelompok dalam situasi tertentu .
Atas dasar itu dapatlah disimpulkan bahwa :
Kepemimpinan adalah : Rangkaian kegiatan penatan berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan .
Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW :
Dalam sepanjang sejarah hidup saya, saya mengidolakan Nabi Muhammad SAW dalam menerapkan sikap kepemimpinannya. Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin dunia yang terbesar sepanjang sejarah. Karena hanya dalam waktu 23 tahun (kurang dari seperempat abad), dengan biaya kurang dari satu persen biaya yang dipergunakan untuk revolusi Perancis dan dengan korban kurang dari seribu orang. Beliau telah menghasilkan tiga karya besar yang belum pernah dicapai oleh pemimpin yang manapun di seluruh dunia sejak Nabi Adam as. sampai sekarang.
Tiga karya besar tersebut adalah:
1. تَوْحِيْدُ الإِلهِ (mengesakan Tuhan)
Nabi Besar Muhammad saw. telah berhasil menjadikan bangsa Arab yang semula mempercayai Tuhan sebanyak 360 (berfaham polytheisme) menjadi bangsa yang memiliki keyakinan tauhid mutlak atau monotheisme absolut.
2. تَوْحِيْدُ الأُمَّةِ (kesatuan ummat)
Nabi Besar Muhammad saw. telah berhasil menjadikan bangsa Arab yang semua selalu melakukan permusuhan dan peperangan antar suku dan antar kabilah, menjadi bangsa yang bersatu padu dalam ikatan keimanan dalam naungan agama Islam.
3. تَوْحِيْدُ الْحُكُوْمَةِ (kesatuan pemerintahan)
Nabi Besar Muhammad saw. telah berhasil membimbing bangsa Arab yang selamanya belum pernah memiliki pemerintahan sendiri yang merdeka dan berdaulat, karena bangsa Arab adalah bangsa yang selalu dijajah oleh Persia dan Romawi, menjadi bangsa yang mampu mendirikan negara kesatuan yang terbentang luas mulai dari benua Afrika sampai Asia.
Kunci dari keberhasilan kepemimpinan beliau dalam waktu relatif singkat itu adalah terletak pada tiga hal:
1. Keunggulan agama Islam
2. Ketepatan sistem dan metode yang beliau pergunakan untuk berda'wah dan memimpin.
3. Kepribadian beliau.
Sistem kepemimpinan yang dipergunakan oleh Nabi Besar Muhammad SAW adalah:
1. Menanamkan benih iman di hati umat manusia dan menggemblengnya sampai benar-benar mantap.
2. Mengajak mereka yang telah memiliki iman yang kuat dan mantap untuk beribadah menjalankan kewajiban-kewajiban agama Islam dengan tekun dan berkesinambungan secara bertahap.
3. Mengajak mereka yang telah kuat dan mantap iman mereka serta telah tekun menjalankan ibadah secara berkelanjutan untuk mengamalkan budi pekerti yang luhur.
Metode dalam kepemimpinan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah:
1. Hikmah, yaitu kata-kata yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dan yang bathil.
2. Nasihat yang baik.
3. Menolak bantahan dari orang-orang yang menentangnya dengan memberikan argumentasi yang jauh lebih baik, sehingga mereka yang menentang dakwah beliau tidak dapat berkutik.
4. Memperlakukan musuh-musuh beliau seperti memperlakukan sahabat karib.
2. PENGARUH KEPEMIMPINAN TERHADAP PERILAKU ORGANISASI
Keberadaan seorang pemimpin dalam organisasi sangat dibutuhkan untuk membawa organisasi kepada tujuan yang telah ditetapkan. Berbagai gaya kepemimpinan akan mewarnai perilaku seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya. Bagaimanapun gaya kepemimpinan seseorang tentunya akan diarahkan untuk kepentingan bersama yaitu kepentingan anggota dan organisasi. Kepemimpinan seseorang dapat mencerminkan karakter pribadinya disamping itu dampak kepemimpinannya akan berpengaruh terhadap Stress kerja dan Komitmen organisasi bawahannya. Seseorang dengan menerima tuntutan tugas yang tinggi akan dapat menimbulkan kemauan yang keras untuk mau mengerjakan suatu kegiatan yang menjadi kewajibannya dan bahkan tidak segan-segan melaksanakan tugas di luar perannya. Adanya tuntutan tugas yang keras dan berat akan dapat menimbulkan Stress kerja, untuk itu dalam menghadapi pekerjaannya, seseorang harus dapat mengelola kondisi stress kerjanya dengan sebaik mungkin. Namun demikian stress kerja tidak selamanya akan menggangu aktivitas seseorang dan bahkan memacu kinerjanya (eustress) dan pada akhirnya dapat menimbulkan Kepuasan kerja.
Mondy, Noe (1996:444) mengatakan:The organization’s research indicates that someworkers who have more control over their jobs, such as college professors and master craftspersons. Begitu pula apabila pengelolaan unsur motivasi diselenggarakan dengan baik, tidak menutup kemungkinan dapat meningkatkan kepuasan kerja sehingga dapat menimbulkan komitmen organisasi yang maksimal bagi karyawan. Tuntutan tugas yang menyenangkan dapat mempengaruhi loyalitas seseorang,hal ini wajar sekali karena jenis tugas akan berdampak pada sikap dan perilaku yang bersangkutan.
Dalam kehidupan modern saat ini, makin terasa betapa pentingnya peranan organisasi terhadapa kepentingan manusia, tidak ada seorang pun di antara manusia ini rasanya yang dilahirkan sampai pada saat kematianny tidak terikat pada organisasi.
Kata organisasi selalu mengandung dua macam pengertian secara umum, yaitu menandakan suatu lembaga atau kelompok fungsional, dan yang lain mengandung arti proses pengorganisasian. Berkembanglah berbagai studi tentang organisasi. Organisasi dapat berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan, alat untuk melindungi, atau alat melestarikan sumber pengetahuan, dan organisasi dipandang sebagai sumber karir. Kepemimpinan sebagai salah satu fungsi manajemen merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan amat berat seolah-olah kepemimpinan dipaksa menghadapi berbagai macam faktor seperti: struktur atau tatanan, koalisi, kekuasaan,dan kondisi lingkungan organisasi. Sebaliknya, kepemimpinan rasanya dapat dengan mudah menjadi satu alat penyelesaian yang luar biasa terhadap persoalan apa saja yang sedang menimpa suatu organisasi.
Dalam hal ini kepemimpinan dapat berperan di dalam melindungi beberapa isu pengaturan organisasi yang tidak tepat, seperti: distribusi kekuasaan yang menjadi penghalang tindakan yang efektif, kekurangan berbagai macam sumber, prosedur yang dianggap buruk, dan sebagainya yaitu masalah - masalah organisasi yang lebih bersifat mendasar. Oleh karena itu peranan sentral kepemimpinan dalam organisasi tersebut, dimensi-dimensi kepemimpinan yang bersifat kompleks perlu dipahami dan dikaji secara terkoordinasi, sehingga peranan kepemimpinan dapat dilaksanakan secara efektif. Dimensi – dimensi tersebut adalah definisi apa yang dimaksud kepemimpinan, berbagai macam studi tentang kepemimpinan, tugas dan fungsi kepemimpinan, efektivitas kepemimpinan, serta usaha – usaha memperbaiki kepemimpinan.
Terkait dengan pengalaman saya sebagai seorang guru, maka saya harus menjadi tolok ukur kemajuan dan perkembangan bagi siswa-siswi yang berada dalam bimbingan saya di dalam pendidikannya. Dunia pendidikan saat ini sudah berkembang begitu pesatnya dari waktu ke waktu. Pendidikan saat ini memang sudah sangat jauh berbeda dengan pendidikan di masa lalu. Perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan sudah sangat pesat sehingga sangat mempengaruhi dunia pendidikan saat ini. Lembaga pendidikan mulai banyak mermunculan sehingga tidak bisa dielakkan akan terjadi persaingan yang sangat ketat diantara lembaga-lembaga pendidikan itu.
Sebagai bagian dari pelaku Lembaga pendidikan, saya mempunyai tanggung jawab sosial yang sangat besar kepada bangsa ini, terutama kepada siswa-siswi didik saya. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi dunia pendidikan diantaranya adalah kepemimpinan seorang kepala sekolah dan guru. Seorang kepala sekolah dan guru adalah seorang pemimpin yang akan menentukan langkah-langkah pendidikan yang efektif di lingkungan sekolah.
Kepemimpinan seorang kepala sekolah dan guru sedikit banyak dapat mempengaruhi pendidikan di lingkungan sekolah. Sekolah juga membutuhkan figur seorang pemimpin yang siap bekerja keras untuk dapat memajukan sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan sekolah yang dipimpinnya. Faktor lain yang berperan mempengaruhi pendidikan adalah kinerja guru yang berkualitas. Seorang guru dituntut untuk dapat memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pendidikan di lingkungan sekolah terutama dalam hal belajar.
Seorang pemimpin bisa disebut berhasil bila atas pengaruhnya orang banyak mau bekerja sama ke arah tujuan-tujuan yang mereka pandang layak dikejar. Seorang pemimpin akan kuat-tegar sepanjang tujuan-tujuan yang dikejarnya sehat. Ia akan disegani berkat tujuan-tujuan yang dicanangkannya, begitu pula halnya dengan seorang guru, dia akan bisa dikatakan berhasil jika sudah mampu membawa anak didiknya menjadi siswa-siswi yang mengalami kemajuan di dalam pelajarannya, mampu menjadi manusia yang lebih edukatif, koperatif dan Agamis, sehingga ada filter yang menjadi pegangan mereka di dalam menjalani kehidupan kelak di dalam masyarakat secara global.
Guru adalah panutan, Tujuan adalah niat, maksud, atau sasaran yang menetapkan bidang hasrat serta arah usaha dari sekumpulan orang yang saling menjalin ikatan. Tujuan-tujuan akan memiliki daya tarik sepanjang pencapaiannya menolong orang banyak meraih sesuatu yang sangat mereka dambakan. Dalam hal ini seorang pemimpin diharapkan lebih mengembangkan relasi antara pemimpin dan pengikut. Pencapaian rasa identitas-diri, pertumbuhan rasa harga diri, pengakuan eksistensi seseorang sebagai pribadi, peneguhan ego seseorang, semua ini merupakan kebutuhan pokok dan mendasar yang dimiliki oleh setiap orang. Para pemimpin yang baik, termasuk guru diantaranya tidak akan pernah melupakan ini.
Guru dituntut memiliki kualitas ketika menyajikan bahan pengajaran kepada subjek didik. Kualitas seorang guru itu dapat diukur dari moralitas, bijaksana, sabar dan menguasai bahan pelajaran ketika beradaptasi dengan subjek didik. Sejumlah faktor itu membuat dirinya mampu menghadapi masalah-masalah sulit, tidak mudah frustasi, depresi atau stress secara positif atau konstruktif, dan tidak destruktif.
Seorang guru mempunyai tanggung jawab terhadap keberhasilan anak didik. Dia tidak hanya dituntut mampu melakukan transformasi seperangkat ilmu pengetahuan kepada peserta didik (cognitive domain) dan aspek keterampilan (pysicomotoric domain), akan tetapi juga mempunyai tanggung jawab untuk mengejewatahkan hal-hal yang berhubungan dengan sikap (affective domain).
Guru yang baik menjadikan Al-Quran sebagai landasan paradigma pemikiran pendidikan Islam, yang dengan nyata telah banyak mengungkapkan analisir kependidikan yang memerlukan perenungan mendalam, terutama bagi praktisi pendidikan. Pemikiran pendidikan yang berlandaskan kepada wahyu Tuhan menuntut terwujudnya suatu sistem pendidikan yang komprehensif, meliputi ketiga pendekatan dalam istilah ilmu pendidikan yaitu cognitive, affective dan psycomotoric. Ketiga pendekatan ini yang nantinya akan mampu melahirkan pribadi-pribadi pendidik yang akan berperan dalam menginternalisasikan nilai-nilai Islam dan mampu mengembangkan peserta didik ke arah pengamalan nilai-nilai Islam secara dinamis dan fleksibel dalam batas-batas konfigurasi realitas wahyu Tuhan.
Karakter kependidikan yang berlandaskan pada pendekatan nilai-nilai Al-Quran saat ini jauh sebagaimana diharapkan. Banyak dari pendidik hanya menonjolkan aspek kemampuan intelektualitas belaka (cognitive) dan meninggalkan nilai-nilai etika (affective domain). Hal ini tidak sesuai dengan nilai-nilai pendidikan yang diajarkan Al-Quran, yang mengajarkan keseimbangan dalam segala hal. Sistem pendidikan yang baik adalah sistem pendidikan yang dapat memadukan tiga aspek tersebut dengan cara mentransferkan pengetahuan serta mewariskan nilai-nilai bagi peserta didik dan generasi selanjutnya. Maka keharusan melahirkan kalangan yang dapat berperan sebagai medium (pendidik) dalam proses pentransferan ilmu, itu kemudian menjadi suatu keniscayaan.
Dari kesenjangan ini, perlu adanya pengkajian kembali nilai-nilai pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai pendidikan Islam. Penjelasan ini diharapkan akan menjadi sebuah solusi dan menjadi sebuah bahan renungan bagi para pendidik, guru dan orang-orang yang concern terhadap dunia pendidikan.
3. UKURAN PERILAKU ORGANISASI
Perilaku organisasi merupakan perilaku manusia dalam kontek menghadapi banyak pilihan atau alternative yang terkait dengan nilai. Perilaku yang menjadi ada nilai baik buruknya, pantas tidak pantaskah, sopan dan tidak sopankah. Masalah penilaian sangat komplek dan perilkau yang penuh dengan tantangan. Dalam menghadapi keharusan memilih supaya mengurangi kesalahan itu, manusia menciptakan norma atau aturan. Norma itu merupakan salah satu yang esensial dalam organisasi. Dalam eksistensinya semua sifat itu ada, namun akan muncul bila sifat itu menjadi dominan. Inilah tantangan yang dihadapi manusia. Makanya harus ada norma sosial, yang mengatur perilaku yang socially. Teori kognitif menjadi tolok ukur terhadap perilaku organisasi.
Implikasi teori kognitif terhadap organisasi :
Membantu memprediksi kecenderungan perubahan sikap maupun perilaku
Indikator Tipe Myers-Briggs (MBTI)
Tes kepribadian dengan 100 pertanyaan tentang bagaimana orang merasa atau bertindak dalam situasi tertentu
Klasifikasi :
1. Ekstrovert atau introvert (E atau I)
2. Indrawi (sensing) atau intuitif (intuitive) (S atau N)
3. Pemikir (thinking) atau perasa (feeling) (Tatau F)
4. Pengertian (perceive) atau penilai (judging) (Patau J)
Tidak ada bukti nyata yang menunjukkan MBTI merupakan pengukuran kepribadian yang valid, namun tetap digunakan dalam organisasi.
5 Faktor penentu perilaku organisasi :
Keekstrovertan :
suka bergaul, banyak bicara, asertif
Keramahtamahan :
baik hati, kooperatif, dapat dipercaya
Kehati-hatian :
bertanggungjawab, dapat diandalkan, tekun,berorientasi pada prestasi
Kestabilan emosi :
tenang, antusias, sanggup menghadapi ketegangan, kegelisahan, kemurungan, ketidakamanan
Keterbukaan terhadap pengalaman :
imajinatif, sensitif secara artistik, cerdas
Menurut Teori Pengharapan, perilaku kerja merupakan fungsi dari tiga karakteristik:
(1) persepsi pegawai bahwa upayanya mengarah pada suatu kinerja
(2) persepsi pegawai bahwa kinerjanya dihargai (misalnya dengan gaji atau pujian)
(3) nilai yang diberikan pegawai terhadap imbalan yang diberikan.
Menurut Vroom’s expectancy theory, perilaku yang diharapkan dalam pekerjaan akan meningkat jika seseorang merasakan adanya hubungan yang positif antara usaha-usaha yang dilakukannya dengan kinerja (Simamora, 1999).
Perilaku-perilaku tersebut selanjutnya meningkat jika ada hubungan positif antara kinerja yang baik dengan imbalan yang mereka terima, terutama imbalan yang bernilai bagi dirinya. Guna mempertahankan individu senantiasa dalam rangkaian perilaku dan kinerja, organisasi harus melakukan evaluasi yang akurat, memberi imbalan dan umpan balik yang tepat.Manusia adalah salah satu dimensi penting dalam organisasi. Kinerja organisasi sangat tergantung pada kinerja individu yang ada di dalamnya. Seluruh pekerjaan dalam sekolah itu, kepala sekolah dan para gurulah yang menentukan keberhasilannya. Sehingga berbagai upaya meningkatkan kualitas sekolah dan anak didik harus dimulai dari perbaikan kualitas kepala sekolah dan guru-gurunya. Oleh karena itu, pemahaman tentang perilaku organisasi menjadi sangat penting dalam rangka meningkatkan kinerjanya di lingkungan sekolah.
Klasifikasi Perilaku Individu Berdasarkan Pekerjaan
Guru merupakan sosok yang begitu dihormati lantaran memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah. Guru sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Ketika orang tua mendaftarkan anaknya ke sekolah, pada saat itu juga ia menaruh harapan terhadap guru, agar anaknya dapat berkembang secara optimal.
Minat, bakat, kemampuan, dan potensi peserta didik tidak akan berkembang secara optimal tanpa bantuan guru. Dalam kaitan ini guru perlu memperhatikan peserta didik secara individual. Tugas guru tidak hanya mengajar, namun juga mendidik, mengasuh, membimbing, dan membentuk kepribadian siswa guna menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM).
Sejauh ini pengamatan saya terhadap lingkungan kerja saya di sekolah, dimana saat ini saya bertugas, banyak karakter dan perilaku individu dari yang sama, hampir sama dan jauh berbeda, sebagaimana saya klasifikasikan pada kelompok berbeda di bawah ini :
1 . Penyendiri vs Peramah
2 . Kecerdasan rendah vs Kecerdasan tinggi
3 . Dipengaruhi oleh perasaan vs Stabil secara emosional
4 . Pengikut vs Dominan
5 . Serius vs Santai
6 . Berani mengambil risiko vs Bijaksana/penuh pertimbangan
7 . Pemalu vs Petualang
8 . Keras hati vs Peka
9 . Mudah percaya vs Pencuriga
10 . Praktis vs Imajinatif
11 . Blak-blakan vs Tersembunyi
12 . Percaya diri vs Mudah cemas
13 . Konservatif vs Suka mencoba
14 . Tergantung pada kelompok vs Mandiri
15 . Tidak terkendali vs Terkendali
16 . Rileks vs Tegang
4. FAKTOR-FAKTOR TERBENTUKNYA PERILAKU ORGANISASI
A. SIKAP
sikap adalah gambaran kepribadian seseorang yang terlahir melalui gerakan fisik dan tanggapan pikiran terhadap suatu keadaan atau suatu objek. Berkowitz, dalam Azwar (2000:5) menerangkan sikap seseorang pada suatu objek adalah perasaan atau emosi, dan faktor kedua adalah reaksi/respon atau kecenderungan untuk bereaksi. Sebagai reaksi maka sikap selalu berhubungan dengan dua alternatif, yaitu senang (like) atau tidak senang (dislike), menurut dan melaksanakan atau menjauhi/menghindari sesuatu.
Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa sikap adalah kecenderungan, pandangan, pendapat atau pendirian seseorang untuk menilai suatu objek atau persoalan dan bertindak sesuai dengan penilaiannya dengan menyadari perasaan positif dan negatif dalam menghadapi suatu objek.
Katz (dalam Walgito, 1990:110) menjelaskan bahwa sikap itu mempunyai empat fungsi, yaitu:
1. Fungsi instrumental atau fungsi penyesuaian, atau fungsi manfaat.
Fungsi ini berkaitan dengan sarana tujuan. Di sini sikap merupakan sarana untuk mencapai tujuan. Orang memandang sampai sejauh mana objek sikap dapat digunakan sebagai sarana dalam mencapai tujuan. Bila objek sikap dapat membantu seseorang dalam mencapai tujuannya, maka orang akan bersikap positif terhadap objek sikap tersebut.
2. Fungsi pertahanan ego
Ini merupakan sikap yang diambil oleh seseorang demi untuk mempertahankan ego atau akunya. Sikap diambil seseorang pada waktu orang yang bersangkutan terancam dalam keadaan dirinya atau egonya, maka dalam keadaan terdesak sikapnya dapat berfungsi sebagai mekanisme pertahanan ego.
3. Fungsi ekspresi nilai
Sikap yang ada pada diri seseorang merupakan jalan bagi individu untuk mengekspresikan nilai yang ada dalam dirinya. Dengan mengekspresikan diri seseorang akan mendapatkan kepuasan dan dapat menunjukkan keadaan dirinya. Dengan mengambil nilai sikap tertentu, akan dapat menggambarkan sistem nilai yang ada pada individu yang bersangkutan.
4. Fungsi pengetahuan
Fungsi ini mempunyai arti bahwa setiap individu mempunyai dorongan untuk ingin tahu. Dengan pengalamannya yang tidak konsisten dengan apa yang diketahui oleh individu, akan disusun kembali atau diubah sedemikian rupa sehingga menjadi konsisten. Ini berarti bila seseorang mempunyai sikap tertentu terhadap suatu objek, menunjukkan tentang pengetahuan orang tersebut objek sikap yang bersangkutan.
Pengalaman di tempat kerja :
Kemampuan Sikap seorang guru, dalam menghadapi kepala sekolah, sesama guru, anak didik, menghadapi orang tua dan karyawan lain di lingkungan sekolah.
B. PERSEPSI
Persepsi, menurut Rakhmat Jalaludin (1998: 51), adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.
Menurut Ruch (1967: 300), persepsi adalah suatu proses tentang petunjukpetunjuk inderawi (sensory) dan pengalaman masa lampau yang relevan diorganisasikan untuk memberikan kepada kita gambaran yang terstruktur dan bermakna pada suatu situasi tertentu.
Senada dengan hal tersebut Atkinson dan Hilgard mengemukakan bahwa persepsi adalah proses dimana kita menafsirkan dan mengorganisasikan pola stimulus dalam lingkungan. Gibson dan Donely menjelaskan bahwa persepsi adalah proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh seorang individu.
Proses pembentukan persepsi dijelaskan oleh Feigi (dalam Yusuf, 1991: 108) sebagai pemaknaan hasil pengamatan yang diawali dengan adanya stimuli. Setelah mendapat stimuli, pada tahap selanjutnya terjadi seleksi yang berinteraksi dengan "interpretation", begitu juga berinteraksi dengan "closure". Proses seleksi terjadi pada saat seseorang memperoleh informasi, maka akan berlangsung proses penyeleksian pesan tentang mana pesan yang dianggap penting dan tidak penting. Proses closure terjadi ketika hasil seleksi tersebut akan disusun menjadi satu kesatuan yang berurutan dan bermakna, sedangkan interpretasi berlangsung ketika yang bersangkutan memberi tafsiran atau makna terhadap informasi tersebut secara menyeluruh.
Persepsi meliputi juga kognisi (pengetahuan), yang mencakup penafsiran objek, tanda dan orang dari sudut pengalaman yang bersangkutan. Selaras dengan pernyataan tersebut Krech, dkk, mengemukakan bahwa persepsi seseorang ditentukan oleh dua faktor utama, yakni pengalaman masa lalu dan faktor pribadi.
Pengalaman di tempat kerja :
Kemampuan Sikap seorang guru, dalam menafsirkan gejala dan sikap dari lingkungan di sekolah, terutama respon anak didik dari caranya mengajar atau berkomunikasi dengan mereka.
C. MOTIVASI
Motivasi adalah faktor yang mendorong orang untuk bertindak dengan cara tertentu. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa motivasi pada dasarnya adalah kondisi mental yang mendorong dilakukannya suatu tindakan (action atau activities) dan memberikan kekuatan (energy) yang mengarah kepada pencapaian kebutuhan, memberi kepuasan ataupun mengurangi ketidakseimbangan. Oleh karena itu tidak akan ada motivasi, jika tidak dirasakan rangsangan-rangsangan terhadap hal semacam di atas yang akan menumbuhkan motivasi, dan motivasi yang telah tumbuh memang dapat menjadikan motor dan dorongan untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan atau pencapaian keseimbangan.
Motivasi adalah dorongan untuk mencapai tujuan tertentu. Dorongan itu bisa saja berbentuk: antusiasme, harapan dan semangat. Semua yang kita lakukan setiap hari senantiasa dibayangi oleh adanya motivasi. Misalnya, seorang karyawan yang bekerja tentu saja memiliki motivasi bekerja, begitu pula seorang atlet memiliki motivasi bertanding, seorang pelajar dengan motivasi belajar, dan lain sebagainya.
Motivasi ibarat api di dalam pikiran seseorang yang terkadang besar membara kadang juga redup, tergantung kondisi mentalnya. Jika seseorang ingin menggapai kesuksesan, motivasi adalah panas api yang harus dijaga jangan sampai padam, karena padamnya motivasi berarti kehilangan bahan bakar untuk menggerakkan mesin tubuh ini untuk menggapai tujuan. Memberikan motivasi adalah menyalakan kembali api motivasi di dalam diri seseorang supaya kembali bersemangat, memiliki keberanian dan pantang menyerah untuk melakukan sesuatu dengan cara tertentu. Kemampuan untuk memberikan motivasi adalah adalah sebuah keterampilan yang bisa dipelajari oleh siapa saja, seorang ibu rumah tangga, mahasiswa, manajer, dan tentu saja pemimpin.
Memotivasi diri sendiri adalah hal yang pokok sebelum kita memotivasi orang lain. Kita harus menciptakan suasana dan keteladanan yang dapat menjadi bahan bakar kita untuk mulai membakar orang lain. Para motivator ulung adalah orang-orang yang dihormati atas keberhasilan mereka sebelumnya.
Di dalam bukunya Successful Motivation in a week, Harvey memberikan pelajaran selama seminggu belajar motivasi diri sendiri dan orang lain secara praktikal. Harvey menyebutkan bahwa calon-calon motivator memiliki sifat-sifat sebagai berikut:
• Positif
• Rasa berterima kasih kepada orang-orang terbaik yang bekerja bersama kita
• Menyadari pentingnya harga diri
Pengalaman di tempat kerja :
Kemampuan seorang guru untuk memotivasi diri sendiri untuk meningkatkan cara mengajar, memotivasi anak didik untuk semangat belajar dan memotivasi sesama guru untuk bahu membahu bekerjasama meningkatkan kualitas belajar mengajar di sekolah.
D. STRESS
Stres itu dimulai dari rasa tidak puas terhadap semua hal yang sedang Anda hadapi dalam hidup Anda ini. Seharusnya Anda menyadari bahwa hidup itu tidak sempurna, dan untuk itu Anda harus memperbaiki ketidaksempurnaan hidup ini dengan pikiran positif. Jangan biarkan hidup Anda dikendalikan oleh nafsu dan hasrat keinginan yang tidak terdefinisi secara jelas. Anda harus memastikan bahwa Anda sangat mengenal dan mengerti tentang semua keinginan hidup Anda. Bila Anda tidak memiliki dasar pijakan hidup yang kuat, maka stres dengan mudah bisa menghancurkan semua mimpi dan cita - cita Anda. Stres itu kapan saja bisa hadir dalam hidup Anda, walaupun Anda tidak pernah mengundangnya untuk datang dalam kehidupan Anda. Tetapi bagi stres, setiap kelemahan dan kelengahan adalah lahan subur untuk tumbuh dan berkembang dengan subur. Anda harus selalu menyiapkan diri Anda sebaik mungkin, agar stres tidak menjadikan diri Anda sebagai tempatnya untuk tumbuh dan berkembang biak.
Sebagai manusia tidaklah mudah untuk hidup dalam pikiran positif yang utuh dan penuh, sebab seribu godaan dan cobaan selalu akan hadir dalam sepanjang hidup Anda, yang mencoba mempengaruhi Anda untuk tidak hidup dalam pikiran positif.
Kebiasaan manusia adalah lebih senang menyebarluaskan berita negatif, dan Anda bisa menyaksikan dan mendengarkan berbagai berita negatif yang menghiasi wajah media masa. Setiap orang dipaksa setiap hari untuk mengisi otak bawah sadarnya dengan pikiran negatif tanpa dia inginkan. Semuanya berproses secara otomatis, dan inilah sumber utama dari stres.
Stres adalah buah dari pikiran negatif. Dan, semua ini dihasilkan dari pola pikir yang selalu lebih menonjolkan sisi buruk dari kehidupan. Mungkin bagi banyak orang dengan membicarakan kekurangan dan kelemahan dari orang lain terasa seperti sebuah sensasi hidup yang mengembirakan, tapi tanpa mereka sadari, mereka telah mengisi pikiran mereka sendiri dengan kata - kata negatif, yang nantinya akan menjadi penyumbang terbesar buat stres yang menyerang diri mereka. Tantangan hidup kita di bumi ini adalah cara kita mengendalikan diri untuk bisa menjalani hidup dalam sebuah keseimbangan yang diisi dengan nilai - nilai kebaikan.
Pengalaman di tempat kerja :
Kemampuan seorang guru untuk mengendalikan emosi dan kejiwaan, sehingga tidak mengalami stress akibat lingkungan di tempat dia mengajar, terutama menghadapi tingkah laku dan sikap anak didik yang mungkin di luar batas-batas normal, sehingga menciptakan kondisi proses belajar mengajar yang kurang menyenangkan.
5. MODEL PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI SEKOLAH
Salah satu masalah pendidikan yang kita hadapi dewasa ini adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan, antara lain memlalui berbagai pelatihan dan peningkatan kualifikasi guru, penyediaan dan perbaikan sarana/prasarana pendidikan, serta peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang merata. Sebagaian sekolah, terutama di kota-kota, menunjukkan peningkatan mutu yang cukup menggembirakan, namun Sebagian lainnya masih memprihatinkan. Dari berbagai pengamatan dan analisis, sedikitnya ada tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata.
Pertama, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan educational production function yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. Pendekatan ini melihat bahwa lembaga pendidikan berfungsi sebagai pusat produksi yang apabila dipilih semua input (masukan) yang diperlukan dalam kegiatan produksi tersebut, maka lembaga ini akan menghasilkan output yang dikehendaki. Dalam kenyataan, mutu pendidikan yang diharapkan tidak terjadi, mengapa? Karena selama ini dalam menerapkan pendekatan education production function terlalu memusatkan pada input pendidikan dan kurang memperhatikan pada proses pendidikan. Padahal, proses pendidikan sangat menentukan output pendidikan.
Kedua, penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara sentralistik, sehingga sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi, yang kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat. Dengan demikian sekolah kehilangan kemandirian, motivasi, dan inisiatif untuk mengembangkan dan memajukan lembaganya termasuk peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional.
Ketiga, peran serta masyarakat, khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat minim. Partisipasi masyarakat pada umumnya selama ini lebih banyak bersifat dukungan dana, bukan pada proses pendidikan (pengambilan keputusan, monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas). Berkaitan dengan akunfabilitas, sekolah tidak mempunyai beban untuk mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pendidikan kepada masyarakat, khususnya orang tua siswa, sebagai salah satu pihak utama yang berkepentingan dengan pendidikan.
Berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan, salah satunya yang sekarang sedang dikembangkan adalah reorientasi penyelenggaraan pendidikan, melalui manajemen sekolah (School Based Management).
Manajemen berbasis sekolah atau School Based Management dapat didefinisikan dan penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengembilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan mutu sekolah dalam pendidikan nasional.
Esensi dari MBS adalah otonomi dan pengambilan keputusan partisipasi untuk mencapai sasaran mutu sekolah. Otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan (kemandirian) yaitu kemandirian dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Jadi, otonomi sekolah adalah kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku. Kemandirian yang-dimaksud harus didukung oleh sejumlah kemampuan, yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan yang terbaik, kemampuan berdemokrasi/menghargai perbedaan pendapat, kemampuan memobilisasi sumber daya, kemampuan memilih cara pelaksanaan yang terbaik, kemampuan berkomunikasi dengan cara yang efektif, kemampuan memecahkan persoalan-persoalan sekolah, kemampuan adaftif dan antisipatif, kemampuan bersinergi danm berkaborasi, dan kemampuan memenuhi kebutuhan sendiri.
Pengambilan keputusan partisipatif adalah suatu cara untuk mengambil keputusan melalui penciptaan lingkungan yang terbuka dan demokratik, di mana warga sekolah (guru, karyawan, siswa,orang tua, tokoh masyarakat) dkjorong untuk terlibatsecara langsung dalam proses pengambilankeputusan yang akan dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan sekolah.
Pengambilan keputusan partisipasi berangkat dari asumsi bahwa jika seseorang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan tersebut, sehingga yang bersangkutan akan merasa memiliki keputusan tersebut, sehingga yang bersangkutan akan bertanggung jawab dan berdedikasi sepenuhnya untuk mencapai tujuan sekolah. Singkatnya makin besar tingkat partisipasi, makin besar pula rasa memiliki, makin besar rasa memiliki, makin besar pula rasa tanggung jawab, dan makin besar rasa tanggung jawab makin besar pula dedikasinya.
Sekolah di Indonesia pasti pernah diajari berkali-kali bagaimana cara pengambilan keputusan melalui musyawarah dan mufakat adalah ciri khas Indonesia. Tentunya cara ini bukanlah satu-satunya cara mengambil keputusan secara kolektif. Misalnya ada cara voting, baik independen (kita tidak bisa melihat pilihan orang lain) atau dependen (setiap orang bisa melihat pilihan orang lain, sehingga pilihan seseorang bisa terpengaruh pilihan orang lain).
Saya yakin setiap cara pengambilan keputusan memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung pada jenis masalah yang dihadapi. Nah, sepertinya menarik untuk mengetahui dalam situatu seperti apa pengambilan keputusan dengan cara voting independen, non-independen dan konsensus menjadi superior.
Kita bisa rancang sebuah eksperimen dimana orang diminta untuk menyelesaikan sebuah masalah. Lalu kita buat tiga kelompok yang masing-masing menggunakan cara pengambilan keputusan yang berbeda, yaitu:
• Voting
Voting adalah memilih calon dari kandidat-kandidat yang ada oleh orang-orang yang memiliki hak ikut serta dalam voting. Yang memiliki hak suara voting memilih kandidat yang dijagokan, dan hasilnya dihitung. Kandidat yang mendapat suara voting tertinggi dialah yang layak manjadi pemenangnya. Contoh : pemilu, pilkada, memilih ketua kelas, dll.
• Konsensus (musyawarah/kesepakatan)
Musyawarah adalah cara efektif melahirkan kemenangan bersama, cara paling bijak untuk menyelesaikan masalah dan cara tepat untuk bersinergi. Setidaknya, ada sembilan resep musyawarah yang bisa kita jalankan. Ke-9 resep itu adalah:
[1]. Sadar realitas.
[2]. Niat dan tekadkan musyawarah sebagai sarana mencari solusi terbaik.
[3]. Berani duduk bersama.
[4]. Miliki keterampilan mendengarkan.
[5]. Miliki keterampilan menjelaskan.
[6]. Miliki keberanian untuk mengambil sisi-sisi kebenaran dari alasan orang lain.
[7]. Berani menurunkan keinginan ideal untuk mendapatkan posisi ideal bersama. Prinsip win win solution menjadi kata kunci.
[8].Bila kesepakan telah dicapai, berusahalah seoptimal mungkin untuk komitmen.
[9]. Semua kesepakatan hanya boleh dilakukan dijalan Allah.
• Cara Undian
Seperti yang kita tahu, undian mirip dengan arisan ibu-ibu dengan mengocok nama-nama kandidat dan nama yang dikeluar setelah di dikocok adalah pemenangnya. Contoh : arisan, undian kartu pos, dan lain-lain.
6. LINGKUNGAN SEKOLAH
Lingkungan merupakan tempat tinggal komunitas tertentu. Sebagai tempat tinggal, lingkungan akan dirawat oleh yang bertempat tinggal sesuai dengan karakternya masing-masing. Oleh karena itu dengan nyata kita dapat membedakan antara lingkungan perumahan elite, lingkungan kampung, lingkungan nelayan, lingkungan rumah kolong, dll. Selain dikarenakan oleh penghuni, lingkungan juga dapat diwarnai oleh fungsi, misalnya prabrik kimia, rumah sakit, apotik, dll. Namun demikian walau fungsi lingkungan sama, tetapi karakteristik penghuni berbeda akan mempengaruhi pula penataan lingkungan. Dari lingkungan kita dapat meneropong karakter / tabiat penghuninya.
Lingkungan sekolah merupakan indikator karakter civitas sekolah maupun kualitas sekolah secara keseluruhan. Sekolah merupakan lingkungan yang dialami oleh anak setiap hari. Lingkungan ini merupakan produk perancangan arsitektur yang dibuat oleh orang dewasa untuk anak. Dalam rangka mendukung pendekatan perancangan yang berorientasi pada kebutuhan pemakai (user-oriented), penelitian ini bermaksud mengungkapkan persepsi anak terhadap lingkungan sekolah melalui analisis gambaran visual tentang lingkungan sekolah yang selama ini dialaminya dan lingkungan sekolah yang diinginkannya. Hasil penelitian ini menunjukkan beragam cara pandang yang digambarkan oleh anak, yang dapat menjadi masukan berharga bagi proses perancangan lingkungan yang berorientasi pada kebutuhan anak.
Lingkungan keluarga yang kondusif bagi pembentukan sifat individu berprestasi tinggi adalah lingkungan Yang menerapkan pola asuh yang otoritatif. Lingkungan sekolah yang kondusif bagi pembentukan sifat individu berprestasi tinggi adalah lingkungan
Sekolah yang menerapkan pola bina yang otoritatif. Ada alur pembentukkan individu berprestasi tingkat 0 yakni diawali dengan pola asuh dan pola bina yang Otoritatif yang keduanya akan berpengaruh terhadap pembentukkan sifat, dan pada akhirnya akan Mempengaruhi prestasi individu.
Dunia pendidikan saat ini sudah berkembang begitu pesatnya dari waktu ke waktu. Pendidikan saat ini memang sudah sangat jauh berbeda dengan pendidikan di masa lalu. Perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan sudah sangat pesat sehingga sangat mempengaruhi dunia pendidikan saat ini. Lembaga pendidikan mulai banyak mermunculan sehingga tidak bisa dielakkan akan terjadi persaingan yang sangat ketat diantara lembaga-lembaga pendidikan itu.Lembaga pendidikan mempunyai tanggung jawab sosial yang sangat besar kepada bangsa ini bukan hanya sekedar untuk kepentingan bisnis semata. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi dunia pendidikan diantaranya adalah kepemimpinan seorang kepala sekolah. Seorang kepala sekolah adalah seorang pemimpin yang akan menentukan langkah-langkah pendidikan yang efektif di lingkungan sekolah.
Kepemimpinan seorang kepala sekolah sedikit banyak dapat mempengaruhi pendidikan di lingkungan sekolah. Sekolah juga membutuhkan figur seorang pemimpin yang siap bekerja keras untuk dapat memajukan sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan sekolah yang dipimpinnya. Faktor lain yang berperan mempengaruhi pendidikan adalah kinerja guru yang berkualitas. Seorang guru dituntut untuk dapat memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pendidikan di lingkungan sekolah terutama dalam hal belajar
Komponen pendidikan yang tidak kalah pentingnya adalah sarana dan prasarana yang mendukung. Mulai dari bangunan fisik, ruang kelas, taman, perpustakaan, laboratorium, sarana olah raga dan kesenian, arena bermain, kantin, perlengkapan kelas, sampai dengan alat peraga edukasi yang dimiliki. Seiring dengan kemajuan bidang informasi dan teknologi, nampaknya bukan hal yang baru sebuah sekolah memiliki fasilitas akses jaringan internet dan website sendiri, dimana setiap stake holders dapat berinteraksi dan berkomunikasi di dunia maya.
Hal ini, akan sangat membantu bagi orang tua untuk memantau perkembangan putra-putrinya secara cepat tanpa harus secara fisik datang kesekolah. Dengan didukung sarana dan prasarana yang baik, diharapkan semua peserta didik dapat belajar secara enjoy, nyaman, dan betah. Sekolah diibaratkan sebagai rumah kedua bagi anak-anak, sehingga sekolah yang baik mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan siswa. Hal yang perlu diperhatikan juga mengenai rasio jumlah siswa dengan luas ruangan kelas serta fasilitas pembelajaran yang lain.
Lokasi sekolah dan lingkungan.
Lokasi yang dimaksud dapat dipandang dari jarak sekolah ke rumah, lingkungan sekitar dan sarana transportasinya. Bisa dibayangkan seorang anak harus bangun pagi-pagi sekali karena letak sekolahnya jauh. Tentu ia pulang dalam keadaan lelah karena jarak yang ditempuhnya memakan waktu yang lama. Belum lagi jika terjadi kemacetan lalu lintas, bisa dimungkinkan sering terlambat pulang maupun masuk sekolahnya.
Lalu kapan ia bisa belajar di rumah dengan nyaman? Bagaimana ia bisa mengembangkan interaksi dengan anggota keluarga lain di rumahnya? Maka, faktor lokasi dan lingkungan ini hendaknya diperhatikan oleh orang tua dan anak itu sendiri dalam menentukan sekolah pilihannya. Perlu dipikirkan juga mengenai sekolah yang berlokasi di pusat perkotaan atau keramaian dan yang berada di pinggiran atau lebih dekat dengan suasana alam, semua memiliki plus-minus-nya.
Dengan Lingkungan sekolah yang menunjang sarana dan prasarananya, diharapkan :
1. Tercapainya kelulusan 100% dengan nilai yang kompetitif
2. Terciptanya suasana belajar yang kondusif dan interaktif.
3. Terciptanya suasana lingkungan sekolah yang agamis dan berwawasan iptek.
4. Tercapainya posisi atas pada ajang kompetisi bidang akademis dan non akademis pada tingkat kabupaten.
5. Terwujudnya suasana kekeluargaan yang kooperatif antarwarga sekolah dan lingkungan sekolah.
6. Terwujudnya partisipasi aktif warga sekolah dan lingkungan sekolah dalam kerangka kegiatan pengembangan dan kemajuan sekolah.
7. Terwujudnya warga sekolah yang tanggap terhadap perkembangan teknologi
7. STRATEGI PERUBAHAN BUDAYA DAN IKLIM SEKOLAH
Budaya sekolah Menurut Deal dan Peterson (1999), budaya sekolah adalah sekumpulan nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol yang dipraktikkan oleh kepala sekolah, guru, petugas administrasi, siswa, dan masyarakat sekitar sekolah.
Budaya sekolah adalah satu elemen sekolah yang teramat penting dan nyata, tetapi sangat sulit untuk mendefinisikannya. Pemahaman terhadap budaya sekolah merupakan salah satu faktor penting dalam struktur reformasi dan kebijakan pendidikan di mana pun. Karena, apa pun jenis perubahan yang diinginkan dalam suatu sistem pendidikan pasti akan mengalami resistensi. Karena itu perlu dilakukan pendefinisian yang bijak tentang budaya sekolah, serta sejauh mana para pengambil kebijakan dan pelaksana sekolah memahami makna budaya sekolah dalam konteks peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.
Pepatah tua dari para antropolog mengatakan, ikan adalah makhluk terakhir yang masuk ke air (Kluckholn, 1949), meskipun ikan hampir dipastikan akan selalu berada di dalam air. Begitu juga budaya sekolah (school culture) dan proses belajar-mengajar, seperti air dan ikan, adalah sebuah keniscayaan dan takdir yang tidak bisa dipisahkan karena keduanya merupakan entitas yang berbeda. Keduanya memberi arti banyak dalam menentukan perspektif dan ragam tindakan pengajaran. Guru dalam konteks budaya dapat memengaruhi setiap aspek dari proses belajar-mengajar (Peterson, 1998). Karena itu, penting dikemukakan hal-hal yang berkaitan dengan budaya sekolah, seperti definisi, efek budaya sekolah terhadap keseluruhan performansi guru dan siswa, dan implikasinya terhadap kebijakan UN dalam konteks budaya sekolah.
Menemukan budaya sekolah
Bayangkan Anda memasuki sebuah sekolah, hal apa kira-kira yang akan Anda lihat dan dengar? Sulit atau mudah memasuki lingkungan sekolah tersebut. Bagaimana cara guru dan siswa menyapa Anda. Bagaimana dengan pengaturan ruang administrasi dan papan demo keterampilan siswa ditata dan ditampilkan, serta ruang kelas dibentuk. Bagaimana suasana belajar-mengajar berlangsung, dan yang tidak kalah pentingnya, bagaimana kondisi kamar kecil (toilet) sekolah. Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan budaya. Sebab, sekolah sedang berusaha memberikan impresi terhadap tamu dan pengunjung lainnya bahwa inilah kami, inilah budaya sekolah kami.
Jika budaya kita definisikan sebagai seperangkat norma, nilai, kepercayaan, dan tradisi yang berlangsung dari waktu ke waktu, budaya sekolah adalah satu set ekspektasi dan asumsi dari norma, nilai, dan tradisi yang secara diam-diam mengarahkan seluruh aktivitas personel sekolah (Peterson, 1998). Karena budaya sekolah bukan suatu entitas statis, maka proses pembentukan norma, nilai, dan tradisi sekolah akan terus berlangsung melalui interaksi dan refleksi terhadap kehidupan dan dunia secara umum (Finnan, 2000). Dalam bahasa Hollins (1996), sebagai agen perubahan, 'sekolah dibentuk oleh praktik dan nilai budaya serta merefleksikan norma-norma dari masyarakat saat mereka masih sedang dikembangkan'. Atau, seperti hidrogen yang merupakan elemen utama air, maka nilai-nilai dalam masyarakat juga merupakan bagian utama dari budaya sekolah.
Tata kelola dan kepemimpinan (leadership) dari pengelola pendidikan dan sekolah juga dapat membentuk budaya sekolah. Dalam konteks ini, kebijakan yang dibuat oleh otoritas pendidikan secara langsung juga dapat memengaruhi budaya sekolah yang sedang dan akan berlangsung. Birokrasi, dengan demikian, dapat menjadi penghambat dan sekaligus stimulus yang konstruktif terhadap keberlangsungan sebuah budaya sekolah yang ingin dan akan dikembangkan oleh komunitas sekolah (Goodlad, 1984; Donahoe, 1997; McLaren, 1999).
Efek budaya sekolah
Budaya dari setiap sekolah bisa jadi memiliki efek positif terhadap proses belajar-mengajar atau sebaliknya memiliki efek negatif serta menghalangi berfungsinya sebuah sekolah. Hanson dan Childs (1998) menggambarkan sekolah dengan suatu iklim sekolah yang positif sebagai 'suatu wadah tempat siswa dan guru saling berbagi dan mereka menggunakan ketulusan hati dalam proses belajar'.
Jika norma-norma dasar pembelajaran seperti pertemanan, kegembiraan dalam proses belajar yang menyenangkan (fun and enjoy learning), manajemen yang terbuka, aturan yang ditegakkan, serta visi-misi sekolah yang terdistribusi dengan baik dalam segenap benak komunitas sekolah, maka sekolah tersebut dapat dikatakan memiliki ciri-ciri budaya sekolah yang positif. Sebaliknya, sebuah sekolah dapat dicirikan memiliki budaya sekolah yang negatif jika tidak memiliki indikator tadi serta adanya penolakan dari guru dan manajemen sekolah untuk melakukan praktik pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan dasar siswa; diayomi dan dilayani sesuai bakat dan minatnya (Peterson dan Deal, 1998).
Terlepas dari apakah positif atau negatif sebuah budaya sekolah, pengenalan terhadap 'perubahan budaya belajar' guru dan siswa harus terus menjadi perhatian seluruh komunitas sekolah. Menurut Sarason (1996), adalah sulit untuk menentukan sifat alami suatu budaya karena kita sendiri memiliki nilai dan tradisi serta kebiasaan yang selalu terbawa ke dalam budaya sekolah. Karena itu, cara pandang kita terhadap nilai-nilai keagamaan, tradisi, kebijakan otoritas pendidikan, kurikulum, dan metodologi pengajaran akan menempati setiap ruang dan relung pikiran siswa dalam proses belajar. Bentuk perubahan apa pun yang akan datang dan ditawarkan kepada komunitas sekolah akan selalu mendapatkan perlawanan dari guru dan siswa, secara tersembunyi maupun terang-terangan. Contoh paling gamblang bagaimana budaya sekolah berlaku dan diterapkan si sekolah-sekolah kita dapat dilihat dari bagaimana sekolah 'memosisikan' diri mereka terhadap kebijakan ujian nasional yang sedang diselenggarakan pemerintah saat ini. Garis dasar untuk perubahan sekolah adalah bahwa supaya perubahan apa pun yang akan datang dan diusulkan otoritas pendidikan harus disesuaikan dengan budaya sekolah.
KONSEP Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) ditengarai banyak pihak sebagai cara mutakhir peningkatan mutu pendidikan di Tanah Air. MBS pada dasarnya merupakan pendelegasian otoritas pengambilan keputusan untuk mengelola sumber daya keuangan, kurikulum, serta profesionalisme guru ke tingkat sekolah. Artinya, segala keputusan yang menyangkut pengelolaan sekolah sedapat mungkin diputuskan oleh pihak terkait dalam lingkungan sekolah, seperti kepala sekolah, guru, orang tua murid, dan tokoh masyarakat setempat yang tergabung dalam dewan sekolah.
Menurut Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, MBS sedang dan telah diujicobakan di 1.000 sekolah. Dari beberapa laporan awal diketahui bahwa dalam penerapannya ternyata konsep ini masih belum menunjukkan hasil yang sepenuhnya memuaskan.
Di satu pihak, sejumlah sekolah yang menerapkan MBS telah mampu mewujudkan proses belajar yang aktif, efektif, dan menyenangkan. MBS berhasil menggalang partisipasi aktif masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan dan transparansi manajemen sekolah.
Di pihak lain, MBS masih belum menyentuh perubahan mendasar dalam meningkatkan sistem pengelolaan pendidikan partisipatif`. Penyebabnya, antara lain, karena lemahnya kepemimpinan kepala sekolah, kurang profesionalnya guru, serta sikap apatis masyarakat.
Dari perspektif sosiologis, kegagalan penerapan MBS bermuara dari tidak adanya perubahan budaya sekolah (school culture), yakni berubahnya semangat, sikap, dan perilaku pihak-pihak yang terkait dengan sekolah. Karenanya, penerapan MBS mensyaratkan tidak hanya perubahan kebijakan legal dan formal, melainkan pula perubahan nilai, semangat, sikap, dan perilaku para aktor sekolah seperti kepala sekolah, guru, orang tua murid, dan siswa.
Penerapan MBS memerlukan perubahan budaya sekolah dari budaya konservatif yang pasif dan sentralistik menjadi budaya inovatif yang egaliter, aktif, dan dinamis. Budaya sekolah Menurut Deal dan Peterson (1999), budaya sekolah adalah sekumpulan nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol yang dipraktikkan oleh kepala sekolah, guru, petugas administrasi, siswa, dan masyarakat sekitar sekolah.
Budaya sekolah merupakan ciri khas, karakter, dan citra sekolah tersebut di masyarakat luas. Untuk mengenali budaya sekolah, cobalah masuk ke sekolah favorit dan sekolah yang mutunya kurang baik (negeri atau swasta).
Perhatikan bagaimana proses belajar-mengajar, disiplin, dan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah tersebut. Kemudian, bandingkan situasi dan kondisi antara dua sekolah tadi. Niscaya akan dirasakan suasana, iklim dan kebiasaan yang sangat berbeda. Suasana, iklim, dan kebiasaan itulah yang dinamakan budaya sekolah.
Menurut Sergiovanni (1999), budaya sekolah memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap suatu proses perubahan berencana (planned change). Karenanya, dalam konteks penerapan MBS, Sergiovanni menyarankan agar para pengambil kebijakan, para penilik, dan kepala sekolah menggunakan pendekatan budaya sekolah atau school culture approach.
Alasannya:
Pertama, pendekatan budaya lebih menitikberatkan faktor manusia di atas faktor-faktor lainnya. Peran manusia amat sentral dalam suatu proses perubahan berencana. Sesuai dengan pepatah man behind the gun, manusia adalah faktor yang menentukan keberhasilan perubahan, bukan struktur atau peraturan legal.
Kedua, pendekatan budaya menekankan pentingnya peran nilai dan keyakinan dalam diri manusia. Aspek ini merupakan elemen yang sangat berpengaruh dalam membentuk sikap dan perilaku. Karenanya, pendekatan budaya menomorsatukan transformasi nilai dan keyakinan terlebih dahulu sebelum perubahan yang bersifat legal-formal.
Ketiga, pendekatan budaya memberikan penghormatan dan penerimaan terhadap perbedaan-perbedaan yang ada. Sikap menerima dan saling hormat akan menciptakan rasa saling percaya dan kebersamaan di antara anggota organisasi. Rasa kebersamaan akan memunculkan kerja sama, dan kerja sama akan mewujudkan sikap profesionalisme.
Strategi perubahan
Strategi perubahan budaya sekolah, kata Deal dan Kennedy (1985), meniscayakan perubahan dalam tiga tataran: yaitu tataran nilai yang dianut, tataran praktik keseharian, dan tataran simbol-simbol budaya.
Dalam tataran nilai, perubahan yang harus dilakukan adalah mengubah nilai-nilai lama yang menghambat dengan nilai baru yang mendukung MBS. Nilai lama yang bercirikan nilai sedang-sedang saja (mediocre values), seperti berpuas diri, tertutup, pasif, dan ketergantungan, harus diubah menjadi nilai baru yang bercirikan nilai keunggulan (excellent values), seperti terbuka terhadap innovasi, kompetitif, berinisiatif, independen, dan bertanggung jawab.
Internalisasi nilai keunggulan ini sangat penting bagi keberhasilan MBS. Tanpa adanya semangat untuk berinovasi, berkompetisi, dan berani menanggung risiko, pelaksanaan MBS hanya akan berjalan di tempat. Tanpa dukungan nilai keunggulan, MBS tidak akan menghasilkan perubahan apa-apa pada kualitas pendidikan di sekolah.
Dalam tataran praktek keseharian, transformasi yang harus dilakukan adalah mengubah sikap dan perilaku lama yang bercirikan `asal-asalan` (asal mengajar, asal datang, dan asal jadi), menjadi sikap dan perilaku baru yang bercirikan kesungguhan dan dedikasi.
Perilaku lama yang cenderung menunggu petunjuk dan berorientasi ke atasan juga direformasi menjadi perilaku baru yang penuh inisiatif dan berorientasi kepada proses belajar siswa.
Perubahan ini dapat diwujudkan melalui tiga hal: pertama, pensosialisasian visi dan misi sekolah sebagai tujuan ideal yang ingin dicapai pada masa mendatang. Kedua, penetapan rencana strategis mingguan atau bulanan sebagai tahapan dan langkah sistematis yang akan dilakukan oleh semua pihak di sekolah. Ketiga, pemberian penghargaan terhadap prestasi guru dan siswa sebagai usaha pembiasaan (habit formation) yang menjunjung sikap dan perilaku yang profesional. Penghargaan dapat berwujud materi maupun nonmateri, seperti ucapan selamat atas prestasi tertentu.
Dalam tataran simbol-simbol budaya, perubahan yang harus dilakukan adalah mengganti simbol budaya yang konservatif dan sentralistik dengan simbol budaya yang dinamis.
Perubahan simbol dapat dilakukan dengan mengubah penataan kelas dan ruang guru, serta pemasangan hasil karya siswa, foto-foto, dan moto. Misalnya, penataan tempat duduk siswa yang berpusat pada guru harus diubah menjadi tempat duduk yang mendorong interaksi antarsiswa sehingga mereka dapat belajar dengan aktif, kreatif, dan menyenangkan. Hasil karya siswa yang berupa gambar, karangan, puisi, dan kerajinan harus dipasang di ruangan kelas untuk mendorong kebanggaan berprestasi. Foto-foto ilmuwan serta karya-karyanya perlu juga perlu dipajang guna merangsang motivasi belajar siswa.
Adalah kurang tepat, untuk tidak mengatakan naif, jika penerapan MBS hanya dilakukan dengan mengubah struktur organisasi atau membentuk dewan sekolah. Pendekatan budaya sekolah sangat diperlukan dalam penerapan MBS. Pelaksanaan MBS meniscayakan proses perubahan pada nilai, semangat, sikap, dan perilaku semua komponen sekolah.
Kepala sekolah dituntut untuk menjadi pemimpin yang proaktif dan berwawasan. Para guru diharapkan bersikap kreatif untuk menggali metode mengajar yang kreatif. Masyarakat dianjurkan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pendidikan di sekolah. Diibaratkan dengan bercocok tanam, MBS adalah bibit unggul tahan hama, sedangkan budaya sekolah adalah sebidang tanah yang akan ditanami. Seunggul dan sebagus apa pun bibit yang akan ditanam, ia tidak akan tumbuh subur jika tanahnya tetap gersang penuh alang-alang.
Budaya sekolah (school culture), itulah kata kunci yang tidak mendapat perhatian secara sungguh-sungguh dari para pengelola pendidikan kita. Budaya sekolah perlu dibangun berdasarkan kekuatan karakteristik budaya lokal masyarakat tempat sekolah itu berada. Budaya sekolah adalah detak jantung sekolah itu sendiri, perumusannya harus dilakukan dengan sebuah komitmen yang jelas dan terukur oleh komunitas sekolah yakni guru, siswa, manajemen sekolah, dan masyarakat.
Sejauh ini strategi perubahan budaya dan iklim sekolah di tempat saya bertugas, tidak mengalami perkembangan yang signifikan, dimana adanya program pemerintah tentang MBS, belum direspon secara menyeluruh, dalam arti hanya faktor-faktor tertentu saja yang sudah diterapkan, tapi belum menyeluruh pelaksanaannya. Pada dasarnya budaya sekolah dimana saya bertugas baik, hanya saja tidak bisa membentuk karakter personality dari seseorang, dalam sekolah kebanyakan yang diajarkan hanya berupa teory yang kurang praktis.
Dan inilah sebuah kesalahan fatal yang telah membudaya hingga saat ini. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa keberadaan sekolah bukanlah hanya sebagai ladang bisnis semata atau hanya ladang mencari ilmu atau mencari nilai atau bahkan hanya tempat mencari ijazah. Tetapi, sekolah juga merupakan contoh sebuah masayarakat kecil dan sebagai tempat pembentukan mental para peserta didik yang kelak akan mengemban tugas bangsa ini.
6. LINGKUNGAN SEKOLAH
Potensi sumber daya manusia merupakan aset nasional sekaligus sebagai modal dasar pembangunan bangsa. Potensi ini hanya dapat digali dan dikembangkan serta dipupuk secara efektif melalui strategi pendidikan dan pembelajaran yang terarah, terpadu, yang dikelola secara serasi dan seimbang dengan memperhatikan pengembangan potensi peserta didik secara utuh dan optimal.
Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas harus didukung dengan lingkungan dan sarana yang sesuai untuk aktivitasnya. Hubungan antara kondisi lingkungan sekolah dengan sikap perilaku untuk anak sekolah dalam proses belajar mengajar belum diperhatikan.
Lingkungan merupakan tempat tinggal komunitas tertentu. Sebagai tempat tinggal, lingkungan akan dirawat oleh yang bertempat tinggal sesuai dengan karakternya masing-masing. Oleh karena itu dengan nyata kita dapat membedakan antara lingkungan perumahan elite, lingkungan kampung, lingkungan nelayan, lingkungan rumah kolong, dll. Selain dikarenakan oleh penghuni, lingkungan juga dapat diwarnai oleh fungsi, misalnya prabrik kimia, rumah sakit, apotik, dll. Namun demikian walau fungsi lingkungan sama, tetapi karakteristik penghuni berbeda akan mempengaruhi pula penataan lingkungan. Dari lingkungan kita dapat meneropong karakter / tabiat penghuninya.
Lingkungan sekolah merupakan indikator karakter civitas sekolah maupun kualitas sekolah secara keseluruhan. Sekolah merupakan lingkungan yang dialami oleh anak setiap hari. Lingkungan ini merupakan produk perancangan arsitektur yang dibuat oleh orang dewasa untuk anak. Dalam rangka mendukung pendekatan perancangan yang berorientasi pada kebutuhan pemakai (user-oriented), penelitian ini bermaksud mengungkapkan persepsi anak terhadap lingkungan sekolah melalui analisis gambaran visual tentang lingkungan sekolah yang selama ini dialaminya dan lingkungan sekolah yang diinginkannya. Hasil penelitian ini menunjukkan beragam cara pandang yang digambarkan oleh anak, yang dapat menjadi masukan berharga bagi proses perancangan lingkungan yang berorientasi pada kebutuhan anak.
Kita harus dapat membuat suasana pertama orang masuk sekolah kita terpukau oleh keindahan halaman depan sekolah. Indah tidak harus mahal, yang penting bersih tertata dan dirawat. Banyak sekolah yang tidak mengurus papan nama, misalnya: huruf rusak, tertutup tanaman, cat pudar, dll.
Banyak sekolah yang membiarkan halaman depan sekolah kosong tidak ada tanaman perindang, tidak ditata dan tidak dirawat.
Lingkungan lain yang harus ditata adalah ruang kelas. Ruang kelas merupakan tempat belajar mengajar. Agar proses belajar mengajar berjalan optimal ruangan harus ditata sedemikian rupa sehingga enak untuk belajar. Berilah gambar atau tanaman yang cocok sehingga membuat suasana menjadi meng-enakkan.
Banyak sekolah yang tidak memperhatikan ruang kelas. Loker dijadikan bak sampah. Meja kursi dibiarkan berantakan setelah ditinggal siswa.
Sepertihalnya ruang kelas, laboratorium juga merupakan tempat transfer knowledge. Suasana Laboratorium identik dengan kekotoran dan kekacauan. Alat dan bahan harus ditata yang rapi. Kalau perlu diberikan hiasan gambar atau tanaman yang sesuai.
Masih ada lingkungan lain diluar kelas dan Lab yang harus ditata, yaitu selasar sekolah dan halaman dalam sekolah. Selasar sekolah dan halaman dalam sekolah biasanya dipergunakan oleh siswa-siswa untuk beristirahat. Karena tidak memperhatikan kebersihan, maka biasanya selasar juga akan kelihatan kumuh. Banyak kertas bekas berserakan, bungkus jajanan tidak dibuang pada tempatnya, dan kondisi lainnya yang lebih buruk lagi.
Menjaga kebersihan merupakan “value” yang harus ditransfer kepada anak didik. Dan kuncinya, apabila pekerjaan kebersihan dilaksanakan secara berkala dan rutin maka tidak akan memberatkan. Misalnya anak diminta membuang sampah ditempatnya. Ada petugas kebersihan yang diatur jadwalnya. Penataan taman dilakukan bersama-sama secara gotong royong sehingga dalam suasana yang menyenangkan, dll.
Beberapa aksi lingkungan yang dapat dilakukan siswa dalam konsep sekolah berbudaya lingkungan antara lain:
a. kegiatan penghijauan
b. bakti sosial lingkungan
c. jalan sehat
d. kerja bakti lingkungan
e. melakukan konservasi lahan dengan penanaman
f. pemeliharaan tanaman
g. pemanfaatan kebun bibit
h. Penambahan koleksi kebun sekolah untuk proses pembelajaran keanekaragaman hayati
i. Perbanyakan tanaman untuk melatih life skill
j. Konservasi flora & fauna
k. pengenalan konsep konservasi
l. implementasi PLH
m. melaksanakan ”Gugur Gunung” atau bedol sekolah
n. monitoring dan evaluasi.
o. penilaian antar kelas.
p. lomba barang bekas
q. mengembangkan produk olahan bahan sekitar
r. mengadakan pameran produk kreasi siswa
Pendidikan mengenai lingkungan sangat penting. Namun pendidikan ini harus memperoleh dukungan lebih dari berbagai unsur yang ada dalam lingkungan sekolah.
Komponen pendidikan yang tidak kalah pentingnya adalah sarana dan prasarana yang mendukung. Mulai dari bangunan fisik, ruang kelas, taman, perpustakaan, laboratorium, sarana olah raga dan kesenian, arena bermain, kantin, perlengkapan kelas, sampai dengan alat peraga edukasi yang dimiliki. Seiring dengan kemajuan bidang informasi dan teknologi, nampaknya bukan hal yang baru sebuah sekolah memiliki fasilitas akses jaringan internet dan website sendiri, dimana setiap stake holders dapat berinteraksi dan berkomunikasi di dunia maya.
Hal ini, akan sangat membantu bagi orang tua untuk memantau perkembangan putra-putrinya secara cepat tanpa harus secara fisik datang kesekolah. Dengan didukung sarana dan prasarana yang baik, diharapkan semua peserta didik dapat belajar secara enjoy, nyaman, dan betah. Sekolah diibaratkan sebagai rumah kedua bagi anak-anak, sehingga sekolah yang baik mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan siswa. Hal yang perlu diperhatikan juga mengenai rasio jumlah siswa dengan luas ruangan kelas serta fasilitas pembelajaran yang lain.
Lokasi sekolah dan lingkungan
Lokasi yang dimaksud dapat dipandang dari jarak sekolah ke rumah, lingkungan sekitar dan sarana transportasinya. Bisa dibayangkan seorang anak harus bangun pagi-pagi sekali karena letak sekolahnya jauh. Tentu ia pulang dalam keadaan lelah karena jarak yang ditempuhnya memakan waktu yang lama. Belum lagi jika terjadi kemacetan lalu lintas, bisa dimungkinkan sering terlambat pulang maupun masuk sekolahnya.
Lalu kapan ia bisa belajar di rumah dengan nyaman? Bagaimana ia bisa mengembangkan interaksi dengan anggota keluarga lain di rumahnya? Maka, faktor lokasi dan lingkungan ini hendaknya diperhatikan oleh orang tua dan anak itu sendiri dalam menentukan sekolah pilihannya. Perlu dipikirkan juga mengenai sekolah yang berlokasi di pusat perkotaan atau keramaian dan yang berada di pinggiran atau lebih dekat dengan suasana alam, semua memiliki plus-minus-nya.
7. STRATEGI PERUBAHAN BUDAYA DAN IKLIM SEKOLAH
KONSEP Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) ditengarai banyak pihak sebagai cara mutakhir peningkatan mutu pendidikan di Tanah Air. MBS pada dasarnya merupakan pendelegasian otoritas pengambilan keputusan untuk mengelola sumber daya keuangan, kurikulum, serta profesionalisme guru ke tingkat sekolah. Artinya, segala keputusan yang menyangkut pengelolaan sekolah sedapat mungkin diputuskan oleh pihak terkait dalam lingkungan sekolah, seperti kepala sekolah, guru, orang tua murid, dan tokoh masyarakat setempat yang tergabung dalam dewan sekolah.
Menurut Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, MBS sedang dan telah diujicobakan di 1.000 sekolah. Dari beberapa laporan awal diketahui bahwa dalam penerapannya ternyata konsep ini masih belum menunjukkan hasil yang sepenuhnya memuaskan.
Di satu pihak, sejumlah sekolah yang menerapkan MBS telah mampu mewujudkan proses belajar yang aktif, efektif, dan menyenangkan. MBS berhasil menggalang partisipasi aktif masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan dan transparansi manajemen sekolah.
Di pihak lain, MBS masih belum menyentuh perubahan mendasar dalam meningkatkan sistem `pengelolaan pendidikan partisipatif`. Penyebabnya, antara lain, karena lemahnya kepemimpinan kepala sekolah, kurang profesionalnya guru, serta sikap apatis masyarakat.
Dari perspektif sosiologis, kegagalan penerapan MBS bermuara dari tidak adanya perubahan budaya sekolah (school culture), yakni berubahnya semangat, sikap, dan perilaku pihak-pihak yang terkait dengan sekolah. Karenanya, penerapan MBS mensyaratkan tidak hanya perubahan kebijakan legal dan formal, melainkan pula perubahan nilai, semangat, sikap, dan perilaku para aktor sekolah seperti kepala sekolah, guru, orang tua murid, dan siswa.
Penerapan MBS memerlukan perubahan budaya sekolah dari budaya konservatif yang pasif dan sentralistik menjadi budaya inovatif yang egaliter, aktif, dan dinamis. Budaya sekolah Menurut Deal dan Peterson (1999), budaya sekolah adalah sekumpulan nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol yang dipraktikkan oleh kepala sekolah, guru, petugas administrasi, siswa, dan masyarakat sekitar sekolah.
Budaya sekolah merupakan ciri khas, karakter, dan citra sekolah tersebut di masyarakat luas. Untuk mengenali budaya sekolah, cobalah masuk ke sekolah favorit dan sekolah yang mutunya kurang baik (negeri atau swasta).
Perhatikan bagaimana proses belajar-mengajar, disiplin, dan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah tersebut. Kemudian, bandingkan situasi dan kondisi antara dua sekolah tadi. Niscaya akan dirasakan suasana, iklim dan kebiasaan yang sangat berbeda. Suasana, iklim, dan kebiasaan itulah yang dinamakan budaya sekolah.
Menurut Sergiovanni (1999), budaya sekolah memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap suatu proses perubahan berencana (planned change). Karenanya, dalam konteks penerapan MBS, Sergiovanni menyarankan agar para pengambil kebijakan, para penilik, dan kepala sekolah menggunakan pendekatan budaya sekolah atau school culture approach.
Alasannya:
Pertama, pendekatan budaya lebih menitikberatkan faktor manusia di atas faktor-faktor lainnya.
Kedua, pendekatan budaya menekankan pentingnya peran nilai dan keyakinan dalam diri manusia.
Ketiga, pendekatan budaya memberikan penghormatan dan penerimaan terhadap perbedaan-perbedaan yang ada.
Strategi perubahan
Strategi perubahan budaya sekolah, kata Deal dan Kennedy (1985), meniscayakan perubahan dalam tiga tataran: yaitu tataran nilai yang dianut, tataran praktik keseharian, dan tataran simbol-simbol budaya.
Dalam tataran nilai, perubahan yang harus dilakukan adalah mengubah nilai-nilai lama yang menghambat dengan nilai baru yang mendukung MBS. Nilai lama yang bercirikan nilai sedang-sedang saja (mediocre values), seperti berpuas diri, tertutup, pasif, dan ketergantungan, harus diubah menjadi nilai baru yang bercirikan nilai keunggulan (excellent values), seperti terbuka terhadap innovasi, kompetitif, berinisiatif, independen, dan bertanggung jawab.
Dalam tataran praktek keseharian, transformasi yang harus dilakukan adalah mengubah sikap dan perilaku lama yang bercirikan `asal-asalan` (asal mengajar, asal datang, dan asal jadi), menjadi sikap dan perilaku baru yang bercirikan kesungguhan dan dedikasi.
Perilaku lama yang cenderung menunggu petunjuk dan berorientasi ke atasan juga direformasi menjadi perilaku baru yang penuh inisiatif dan berorientasi kepada proses belajar siswa.
Perubahan ini dapat diwujudkan melalui tiga hal: Pertama, pensosialisasian visi dan misi sekolah sebagai tujuan ideal yang ingin dicapai pada masa mendatang. Kedua, penetapan rencana strategis mingguan atau bulanan sebagai tahapan dan langkah sistematis yang akan dilakukan oleh semua pihak di sekolah. Ketiga, pemberian penghargaan terhadap prestasi guru dan siswa sebagai usaha pembiasaan (habit formation) yang menjunjung sikap dan perilaku yang profesional. Penghargaan dapat berwujud materi maupun nonmateri, seperti ucapan selamat atas prestasi tertentu.
Dalam tataran simbol-simbol budaya, perubahan yang harus dilakukan adalah mengganti simbol budaya yang konservatif dan sentralistik dengan simbol budaya yang dinamis.
Perubahan simbol dapat dilakukan dengan mengubah penataan kelas dan ruang guru, serta pemasangan hasil karya siswa, foto-foto, dan moto.
Misalnya, penataan tempat duduk siswa yang berpusat pada guru harus diubah menjadi tempat duduk yang mendorong interaksi antarsiswa sehingga mereka dapat belajar dengan aktif, kreatif, dan menyenangkan. Hasil karya siswa yang berupa gambar, karangan, puisi, dan kerajinan harus dipasang di ruangan kelas untuk mendorong kebanggaan berprestasi. Foto-foto ilmuwan serta karya-karyanya perlu juga perlu dipajang guna merangsang motivasi belajar siswa.
Sangat perlu.
Adalah kurang tepat, untuk tidak mengatakan naif, jika penerapan MBS hanya dilakukan dengan mengubah struktur organisasi atau membentuk dewan sekolah. Pendekatan budaya sekolah sangat diperlukan dalam penerapan MBS. Pelaksanaan MBS meniscayakan proses perubahan pada nilai, semangat, sikap, dan perilaku semua komponen sekolah.
Sejauh ini strategi perubahan budaya dan iklim sekolah di tempat saya bertugas, tidak mengalami perkembangan yang signifikan, dimana adanya program pemerintah tentang MBS, belum direspon secara menyeluruh, dalam arti hanya faktor-faktor tertentu saja yang sudah diterapkan, tapi belum menyeluruh pelaksanaannya.
8. PERILAKU KELAS DIDIK MENERIMA PEMBELAJARAN SEMESTER INI
Saya mengamati dengan seksama siswa-siswi di kelas dan mencatat dengan detail 4 gejala-gejala perilaku yang khusus.
1. Ciri perilaku Pembosan
2. Ciri perilaku Pemalu
3. Ciri perilaku Penakut
4. Ciri perilaku Bersemangat
5. Ciri perilaku Penyendiri
Cara yang saya gunakan merupakan cara yang klasik dan tiap hari dilakukan entah berapa tahun berjalan. Cara itu biasanya tanya jawab, langsung perintah buka buku, langsung menerangkan, dan langsung menyuruh siswa. Cara lain tidak pernah dilakukan.
Tapi saya juga melakukan variasi agar siswa senang dalam belajar. Berikut ini metode mengajar yang saya pakai untuk menambah cara mengajar yang lama.
Berangkat dari Siswa
Memulai pelajaran dari diri siswa. Mengamati dengan cepat siswa yang hadir kemudian memulai dari siswa yang diamati tersebut.
Contoh, jika saya akan membahas pemilu, berangkat dari siswa yang halaman rumahnya digunakan untuk pilkada. Begitu pula, kalau saya akan mengajar tentang mencangkok, berangkat dari bentuk cangkok dari rumah atau halaman rumah siswa.
Berangkat dari Isu Nasional
Isu nasional datang bertubi-tubi tanpa henti. Banyak isu yang menarik untuk dijadikan bahan memulai pembelajaran. Saya memulai dari isu nasional kemudian masuk ke inti pelajaran.
Berangkat dari Kejadian
Kejadian yang telah lalu, yang dialami siswa atau saya sendiri dapat digunakan untuk memulai pelajaran. Saya memulai bercerita tentang pengalaman yang baru saja saya alami.
Contoh, untuk masuk ke topik mengukur bidang datar, saya dapat memulai dengan pengalaman bermain voley.
Berangkat dari Gambar
Saya membawa gambar beraneka bentuk, besar-besar ukurannya, atau kecil-kecil. Gambar itu dipakai untuk memulai pelajaran dengan menarik.
Berangkat dari Teka-Teki
Banyak teka-teki yang menarik untuk digunakan memulai pelajaran. Dari teka-teki, siswa langsung mengolah pikiran yang berkaitan dengan topik.
Berangkat dari Benda Sekitar
Saya membawa benda sekitar untuk memulai mengajar, yakni batu, kerikil, tanaman, daun, akar, dan sebagainya. Siswa saya ajak untuk mengidentifikasi benda sekitar itu sebelum ke pembahasan inti.
Berangkat dari Film dan Siaran Radio
Saat memulai pelajaran, saya ajak anak menonton film singkat atau rekaman siaran radio. Kemudian, saya memancing pertanyaan dari isi film atau radio. Kemudian memulai dengan pelajaran initinya.
Masih banyak lagi cara memulai pelajaran yang lebih menyenangkan. Misalnya melalui baca puisi, cerita singkat/dongeng, lagu, gerakan tubuh, boneka, yel-yel, dan yang lainnya. Saya tidak menutup diri dalam memulai mengajar hanya dengan tanya jawab.
Sekolah adalah tempat belajar bagi siswa. Maka tugas saya sebagai guru di kelas adalah "membantu siswa belajar", dengan mengatur Proses Belajar - Mengajar serta menyediakan kondisi belajar yang optimal. Saya tidak hanya seorang pengajar, tetapi juga seorang manajer kelas. Di kelas ada dua kegiatan yang memang berhubungan erat satu sama lain, namun dapat dan harus dibedakan karena tujuan dan sifat- sifatnya memang berlainan
Dalam kelas dapat muncul masalah pengajaran atau masalah pengelolaan. Karena itu setiap masalah yang timbul di kelas perlu ditanggulangi sesuai dengan sifat masalahnya. Masalah pengelolaan kelas terjadi bila ada kesenjangan antara tingkat keterlibatan siswa yang seharusnya dalam proses belajar - mengajar dengan keterlibatan yang nyata- nyata terjadi.
Kesenjangan ini dapat terjadi karena berbagai sebab, yaitu orang (siswa, guru), sarana (misalnya media pengajaran dan fasilitas fisik) dan organisasi (misalnya: perubahan jadwal, pergantian guru, dsb.).
Pada dasarnya, setiap orang adalah pemimpin. Sekurang-kurangnya ia menjadi pemimpin atas dirinya sendiri. Konsekuensi kepemimpinan adalah pertanggungjawaban, sesuai dengan sistem dan mekanisme yang telah ditetapkan.
Kepemimpinan adalah pencerminan pola pikir, sikap, dan tindak sebagai hasil keterpaduan nilai, norma, ilmu, seni, watak, dan keperibadian. Sehingga dalam bentuk penampilan dan perilaku karakteristiknya sangat bervariasi:
1. Egoistik,
2. Paternalistik,
3. Materialistik,
4. Kharismatik,
5. Demokratik,
6. Universalistik,
7. Altruistik,
8. Profetik.
Kepemimpinan adalah suatu peran dan proses untuk mempengaruhi, menggerakkan, dan mengarahkan orang lain, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan suatu cara yang tidak memaksa. Sehingga orang bekerja dengan kesadaran, motivasi, etos, etik, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan (perundangan, prinsip, metoda, job-description, individual, team work).
Pemimpin adalah anggota dari suatu perkumpulan yang diberi kedudukan tertentu dan bertindak sesuai dengan kedudukannya. Seorang pemimpin adalah juga seorang ahli dalam perkumpulan yang diharapkan menggunakan pengaruhnya dalam mewujudkan dan mencapai tujuan kelompok. Pemimpin yang sebenarnya ialah seorang yang memimpin dan bukan seorang yang menggunakan kedudukannya untuk memimpin. Karenanya, ia pun sekaligus sebagai pengawas dan pengikut.
Ada beberapa teori tentang kepemimpinan, diantaranya :
1. Ordway Tead (1935)
Kepemimpinan adalah aktifitas mempengaruhi orang- orang agar mau bekerja sama untuk mencapai beberapa tujuan yang mereka inginkan.
2. Refter (1941)
Kepemimpinan adalah sesuatu kemampuan untuk mengajak atau mengarahkan orang orang tanpa memakai pembawa atau kekuatan formal jabatan atau keadan luar .
3. G. L. Freeman atau E. K. Taylor (1950)
Kepemimpinan adalah kemampuan untuk menciptakan kegiatan kelompok mencapai tujuan organisasi sehingga efektifitas maksimum dan kerjasama dari tiap-tiap individu.
4. Ralp M. Stogdill
Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan- kegiatan sekelompok orang yang terorganisir dalam usaha mereka menepatkan tujuan dan mencapainya
5. Franklyn S. Haiman (1951)
Kepemimpinan adalah suatu usaha untuk mengarahkan prilaku orang lain guna mencapai tujuan khusus.
6. Dubin (1951)
Kepemimpinan adalah menggunakan wewenang dan membuat keputusan- keputusan
7. Fred E. Tiedler (1967)
Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas kelompok untuk menentukan tujuan dan mencapainya.
8. Harold Koontz dan Cyrill O. Ddonnell (1976)
Kepemimpinan adalah seni membujuk bawahan untuk menyelesaikan pekerjaan- pekerjaan mereka dengan semangat keyakinan.
9. Keith Devis (1977)
Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mengajak orang lain untuk mencapai tujuan tertentu dengan penuh semangat.
10. Paul Hersey dan Kenneth H. Blanchard (1982)
Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan individu atau kelompok dalam situasi tertentu .
Atas dasar itu dapatlah disimpulkan bahwa :
Kepemimpinan adalah : Rangkaian kegiatan penatan berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan .
Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW :
Dalam sepanjang sejarah hidup saya, saya mengidolakan Nabi Muhammad SAW dalam menerapkan sikap kepemimpinannya. Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin dunia yang terbesar sepanjang sejarah. Karena hanya dalam waktu 23 tahun (kurang dari seperempat abad), dengan biaya kurang dari satu persen biaya yang dipergunakan untuk revolusi Perancis dan dengan korban kurang dari seribu orang. Beliau telah menghasilkan tiga karya besar yang belum pernah dicapai oleh pemimpin yang manapun di seluruh dunia sejak Nabi Adam as. sampai sekarang.
Tiga karya besar tersebut adalah:
1. تَوْحِيْدُ الإِلهِ (mengesakan Tuhan)
Nabi Besar Muhammad saw. telah berhasil menjadikan bangsa Arab yang semula mempercayai Tuhan sebanyak 360 (berfaham polytheisme) menjadi bangsa yang memiliki keyakinan tauhid mutlak atau monotheisme absolut.
2. تَوْحِيْدُ الأُمَّةِ (kesatuan ummat)
Nabi Besar Muhammad saw. telah berhasil menjadikan bangsa Arab yang semua selalu melakukan permusuhan dan peperangan antar suku dan antar kabilah, menjadi bangsa yang bersatu padu dalam ikatan keimanan dalam naungan agama Islam.
3. تَوْحِيْدُ الْحُكُوْمَةِ (kesatuan pemerintahan)
Nabi Besar Muhammad saw. telah berhasil membimbing bangsa Arab yang selamanya belum pernah memiliki pemerintahan sendiri yang merdeka dan berdaulat, karena bangsa Arab adalah bangsa yang selalu dijajah oleh Persia dan Romawi, menjadi bangsa yang mampu mendirikan negara kesatuan yang terbentang luas mulai dari benua Afrika sampai Asia.
Kunci dari keberhasilan kepemimpinan beliau dalam waktu relatif singkat itu adalah terletak pada tiga hal:
1. Keunggulan agama Islam
2. Ketepatan sistem dan metode yang beliau pergunakan untuk berda'wah dan memimpin.
3. Kepribadian beliau.
Sistem kepemimpinan yang dipergunakan oleh Nabi Besar Muhammad SAW adalah:
1. Menanamkan benih iman di hati umat manusia dan menggemblengnya sampai benar-benar mantap.
2. Mengajak mereka yang telah memiliki iman yang kuat dan mantap untuk beribadah menjalankan kewajiban-kewajiban agama Islam dengan tekun dan berkesinambungan secara bertahap.
3. Mengajak mereka yang telah kuat dan mantap iman mereka serta telah tekun menjalankan ibadah secara berkelanjutan untuk mengamalkan budi pekerti yang luhur.
Metode dalam kepemimpinan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah:
1. Hikmah, yaitu kata-kata yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dan yang bathil.
2. Nasihat yang baik.
3. Menolak bantahan dari orang-orang yang menentangnya dengan memberikan argumentasi yang jauh lebih baik, sehingga mereka yang menentang dakwah beliau tidak dapat berkutik.
4. Memperlakukan musuh-musuh beliau seperti memperlakukan sahabat karib.
2. PENGARUH KEPEMIMPINAN TERHADAP PERILAKU ORGANISASI
Keberadaan seorang pemimpin dalam organisasi sangat dibutuhkan untuk membawa organisasi kepada tujuan yang telah ditetapkan. Berbagai gaya kepemimpinan akan mewarnai perilaku seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya. Bagaimanapun gaya kepemimpinan seseorang tentunya akan diarahkan untuk kepentingan bersama yaitu kepentingan anggota dan organisasi. Kepemimpinan seseorang dapat mencerminkan karakter pribadinya disamping itu dampak kepemimpinannya akan berpengaruh terhadap Stress kerja dan Komitmen organisasi bawahannya. Seseorang dengan menerima tuntutan tugas yang tinggi akan dapat menimbulkan kemauan yang keras untuk mau mengerjakan suatu kegiatan yang menjadi kewajibannya dan bahkan tidak segan-segan melaksanakan tugas di luar perannya. Adanya tuntutan tugas yang keras dan berat akan dapat menimbulkan Stress kerja, untuk itu dalam menghadapi pekerjaannya, seseorang harus dapat mengelola kondisi stress kerjanya dengan sebaik mungkin. Namun demikian stress kerja tidak selamanya akan menggangu aktivitas seseorang dan bahkan memacu kinerjanya (eustress) dan pada akhirnya dapat menimbulkan Kepuasan kerja.
Mondy, Noe (1996:444) mengatakan:The organization’s research indicates that someworkers who have more control over their jobs, such as college professors and master craftspersons. Begitu pula apabila pengelolaan unsur motivasi diselenggarakan dengan baik, tidak menutup kemungkinan dapat meningkatkan kepuasan kerja sehingga dapat menimbulkan komitmen organisasi yang maksimal bagi karyawan. Tuntutan tugas yang menyenangkan dapat mempengaruhi loyalitas seseorang,hal ini wajar sekali karena jenis tugas akan berdampak pada sikap dan perilaku yang bersangkutan.
Dalam kehidupan modern saat ini, makin terasa betapa pentingnya peranan organisasi terhadapa kepentingan manusia, tidak ada seorang pun di antara manusia ini rasanya yang dilahirkan sampai pada saat kematianny tidak terikat pada organisasi.
Kata organisasi selalu mengandung dua macam pengertian secara umum, yaitu menandakan suatu lembaga atau kelompok fungsional, dan yang lain mengandung arti proses pengorganisasian. Berkembanglah berbagai studi tentang organisasi. Organisasi dapat berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan, alat untuk melindungi, atau alat melestarikan sumber pengetahuan, dan organisasi dipandang sebagai sumber karir. Kepemimpinan sebagai salah satu fungsi manajemen merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan amat berat seolah-olah kepemimpinan dipaksa menghadapi berbagai macam faktor seperti: struktur atau tatanan, koalisi, kekuasaan,dan kondisi lingkungan organisasi. Sebaliknya, kepemimpinan rasanya dapat dengan mudah menjadi satu alat penyelesaian yang luar biasa terhadap persoalan apa saja yang sedang menimpa suatu organisasi.
Dalam hal ini kepemimpinan dapat berperan di dalam melindungi beberapa isu pengaturan organisasi yang tidak tepat, seperti: distribusi kekuasaan yang menjadi penghalang tindakan yang efektif, kekurangan berbagai macam sumber, prosedur yang dianggap buruk, dan sebagainya yaitu masalah - masalah organisasi yang lebih bersifat mendasar. Oleh karena itu peranan sentral kepemimpinan dalam organisasi tersebut, dimensi-dimensi kepemimpinan yang bersifat kompleks perlu dipahami dan dikaji secara terkoordinasi, sehingga peranan kepemimpinan dapat dilaksanakan secara efektif. Dimensi – dimensi tersebut adalah definisi apa yang dimaksud kepemimpinan, berbagai macam studi tentang kepemimpinan, tugas dan fungsi kepemimpinan, efektivitas kepemimpinan, serta usaha – usaha memperbaiki kepemimpinan.
Terkait dengan pengalaman saya sebagai seorang guru, maka saya harus menjadi tolok ukur kemajuan dan perkembangan bagi siswa-siswi yang berada dalam bimbingan saya di dalam pendidikannya. Dunia pendidikan saat ini sudah berkembang begitu pesatnya dari waktu ke waktu. Pendidikan saat ini memang sudah sangat jauh berbeda dengan pendidikan di masa lalu. Perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan sudah sangat pesat sehingga sangat mempengaruhi dunia pendidikan saat ini. Lembaga pendidikan mulai banyak mermunculan sehingga tidak bisa dielakkan akan terjadi persaingan yang sangat ketat diantara lembaga-lembaga pendidikan itu.
Sebagai bagian dari pelaku Lembaga pendidikan, saya mempunyai tanggung jawab sosial yang sangat besar kepada bangsa ini, terutama kepada siswa-siswi didik saya. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi dunia pendidikan diantaranya adalah kepemimpinan seorang kepala sekolah dan guru. Seorang kepala sekolah dan guru adalah seorang pemimpin yang akan menentukan langkah-langkah pendidikan yang efektif di lingkungan sekolah.
Kepemimpinan seorang kepala sekolah dan guru sedikit banyak dapat mempengaruhi pendidikan di lingkungan sekolah. Sekolah juga membutuhkan figur seorang pemimpin yang siap bekerja keras untuk dapat memajukan sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan sekolah yang dipimpinnya. Faktor lain yang berperan mempengaruhi pendidikan adalah kinerja guru yang berkualitas. Seorang guru dituntut untuk dapat memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pendidikan di lingkungan sekolah terutama dalam hal belajar.
Seorang pemimpin bisa disebut berhasil bila atas pengaruhnya orang banyak mau bekerja sama ke arah tujuan-tujuan yang mereka pandang layak dikejar. Seorang pemimpin akan kuat-tegar sepanjang tujuan-tujuan yang dikejarnya sehat. Ia akan disegani berkat tujuan-tujuan yang dicanangkannya, begitu pula halnya dengan seorang guru, dia akan bisa dikatakan berhasil jika sudah mampu membawa anak didiknya menjadi siswa-siswi yang mengalami kemajuan di dalam pelajarannya, mampu menjadi manusia yang lebih edukatif, koperatif dan Agamis, sehingga ada filter yang menjadi pegangan mereka di dalam menjalani kehidupan kelak di dalam masyarakat secara global.
Guru adalah panutan, Tujuan adalah niat, maksud, atau sasaran yang menetapkan bidang hasrat serta arah usaha dari sekumpulan orang yang saling menjalin ikatan. Tujuan-tujuan akan memiliki daya tarik sepanjang pencapaiannya menolong orang banyak meraih sesuatu yang sangat mereka dambakan. Dalam hal ini seorang pemimpin diharapkan lebih mengembangkan relasi antara pemimpin dan pengikut. Pencapaian rasa identitas-diri, pertumbuhan rasa harga diri, pengakuan eksistensi seseorang sebagai pribadi, peneguhan ego seseorang, semua ini merupakan kebutuhan pokok dan mendasar yang dimiliki oleh setiap orang. Para pemimpin yang baik, termasuk guru diantaranya tidak akan pernah melupakan ini.
Guru dituntut memiliki kualitas ketika menyajikan bahan pengajaran kepada subjek didik. Kualitas seorang guru itu dapat diukur dari moralitas, bijaksana, sabar dan menguasai bahan pelajaran ketika beradaptasi dengan subjek didik. Sejumlah faktor itu membuat dirinya mampu menghadapi masalah-masalah sulit, tidak mudah frustasi, depresi atau stress secara positif atau konstruktif, dan tidak destruktif.
Seorang guru mempunyai tanggung jawab terhadap keberhasilan anak didik. Dia tidak hanya dituntut mampu melakukan transformasi seperangkat ilmu pengetahuan kepada peserta didik (cognitive domain) dan aspek keterampilan (pysicomotoric domain), akan tetapi juga mempunyai tanggung jawab untuk mengejewatahkan hal-hal yang berhubungan dengan sikap (affective domain).
Guru yang baik menjadikan Al-Quran sebagai landasan paradigma pemikiran pendidikan Islam, yang dengan nyata telah banyak mengungkapkan analisir kependidikan yang memerlukan perenungan mendalam, terutama bagi praktisi pendidikan. Pemikiran pendidikan yang berlandaskan kepada wahyu Tuhan menuntut terwujudnya suatu sistem pendidikan yang komprehensif, meliputi ketiga pendekatan dalam istilah ilmu pendidikan yaitu cognitive, affective dan psycomotoric. Ketiga pendekatan ini yang nantinya akan mampu melahirkan pribadi-pribadi pendidik yang akan berperan dalam menginternalisasikan nilai-nilai Islam dan mampu mengembangkan peserta didik ke arah pengamalan nilai-nilai Islam secara dinamis dan fleksibel dalam batas-batas konfigurasi realitas wahyu Tuhan.
Karakter kependidikan yang berlandaskan pada pendekatan nilai-nilai Al-Quran saat ini jauh sebagaimana diharapkan. Banyak dari pendidik hanya menonjolkan aspek kemampuan intelektualitas belaka (cognitive) dan meninggalkan nilai-nilai etika (affective domain). Hal ini tidak sesuai dengan nilai-nilai pendidikan yang diajarkan Al-Quran, yang mengajarkan keseimbangan dalam segala hal. Sistem pendidikan yang baik adalah sistem pendidikan yang dapat memadukan tiga aspek tersebut dengan cara mentransferkan pengetahuan serta mewariskan nilai-nilai bagi peserta didik dan generasi selanjutnya. Maka keharusan melahirkan kalangan yang dapat berperan sebagai medium (pendidik) dalam proses pentransferan ilmu, itu kemudian menjadi suatu keniscayaan.
Dari kesenjangan ini, perlu adanya pengkajian kembali nilai-nilai pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai pendidikan Islam. Penjelasan ini diharapkan akan menjadi sebuah solusi dan menjadi sebuah bahan renungan bagi para pendidik, guru dan orang-orang yang concern terhadap dunia pendidikan.
3. UKURAN PERILAKU ORGANISASI
Perilaku organisasi merupakan perilaku manusia dalam kontek menghadapi banyak pilihan atau alternative yang terkait dengan nilai. Perilaku yang menjadi ada nilai baik buruknya, pantas tidak pantaskah, sopan dan tidak sopankah. Masalah penilaian sangat komplek dan perilkau yang penuh dengan tantangan. Dalam menghadapi keharusan memilih supaya mengurangi kesalahan itu, manusia menciptakan norma atau aturan. Norma itu merupakan salah satu yang esensial dalam organisasi. Dalam eksistensinya semua sifat itu ada, namun akan muncul bila sifat itu menjadi dominan. Inilah tantangan yang dihadapi manusia. Makanya harus ada norma sosial, yang mengatur perilaku yang socially. Teori kognitif menjadi tolok ukur terhadap perilaku organisasi.
Implikasi teori kognitif terhadap organisasi :
Membantu memprediksi kecenderungan perubahan sikap maupun perilaku
Indikator Tipe Myers-Briggs (MBTI)
Tes kepribadian dengan 100 pertanyaan tentang bagaimana orang merasa atau bertindak dalam situasi tertentu
Klasifikasi :
1. Ekstrovert atau introvert (E atau I)
2. Indrawi (sensing) atau intuitif (intuitive) (S atau N)
3. Pemikir (thinking) atau perasa (feeling) (Tatau F)
4. Pengertian (perceive) atau penilai (judging) (Patau J)
Tidak ada bukti nyata yang menunjukkan MBTI merupakan pengukuran kepribadian yang valid, namun tetap digunakan dalam organisasi.
5 Faktor penentu perilaku organisasi :
Keekstrovertan :
suka bergaul, banyak bicara, asertif
Keramahtamahan :
baik hati, kooperatif, dapat dipercaya
Kehati-hatian :
bertanggungjawab, dapat diandalkan, tekun,berorientasi pada prestasi
Kestabilan emosi :
tenang, antusias, sanggup menghadapi ketegangan, kegelisahan, kemurungan, ketidakamanan
Keterbukaan terhadap pengalaman :
imajinatif, sensitif secara artistik, cerdas
Menurut Teori Pengharapan, perilaku kerja merupakan fungsi dari tiga karakteristik:
(1) persepsi pegawai bahwa upayanya mengarah pada suatu kinerja
(2) persepsi pegawai bahwa kinerjanya dihargai (misalnya dengan gaji atau pujian)
(3) nilai yang diberikan pegawai terhadap imbalan yang diberikan.
Menurut Vroom’s expectancy theory, perilaku yang diharapkan dalam pekerjaan akan meningkat jika seseorang merasakan adanya hubungan yang positif antara usaha-usaha yang dilakukannya dengan kinerja (Simamora, 1999).
Perilaku-perilaku tersebut selanjutnya meningkat jika ada hubungan positif antara kinerja yang baik dengan imbalan yang mereka terima, terutama imbalan yang bernilai bagi dirinya. Guna mempertahankan individu senantiasa dalam rangkaian perilaku dan kinerja, organisasi harus melakukan evaluasi yang akurat, memberi imbalan dan umpan balik yang tepat.Manusia adalah salah satu dimensi penting dalam organisasi. Kinerja organisasi sangat tergantung pada kinerja individu yang ada di dalamnya. Seluruh pekerjaan dalam sekolah itu, kepala sekolah dan para gurulah yang menentukan keberhasilannya. Sehingga berbagai upaya meningkatkan kualitas sekolah dan anak didik harus dimulai dari perbaikan kualitas kepala sekolah dan guru-gurunya. Oleh karena itu, pemahaman tentang perilaku organisasi menjadi sangat penting dalam rangka meningkatkan kinerjanya di lingkungan sekolah.
Klasifikasi Perilaku Individu Berdasarkan Pekerjaan
Guru merupakan sosok yang begitu dihormati lantaran memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah. Guru sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Ketika orang tua mendaftarkan anaknya ke sekolah, pada saat itu juga ia menaruh harapan terhadap guru, agar anaknya dapat berkembang secara optimal.
Minat, bakat, kemampuan, dan potensi peserta didik tidak akan berkembang secara optimal tanpa bantuan guru. Dalam kaitan ini guru perlu memperhatikan peserta didik secara individual. Tugas guru tidak hanya mengajar, namun juga mendidik, mengasuh, membimbing, dan membentuk kepribadian siswa guna menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM).
Sejauh ini pengamatan saya terhadap lingkungan kerja saya di sekolah, dimana saat ini saya bertugas, banyak karakter dan perilaku individu dari yang sama, hampir sama dan jauh berbeda, sebagaimana saya klasifikasikan pada kelompok berbeda di bawah ini :
1 . Penyendiri vs Peramah
2 . Kecerdasan rendah vs Kecerdasan tinggi
3 . Dipengaruhi oleh perasaan vs Stabil secara emosional
4 . Pengikut vs Dominan
5 . Serius vs Santai
6 . Berani mengambil risiko vs Bijaksana/penuh pertimbangan
7 . Pemalu vs Petualang
8 . Keras hati vs Peka
9 . Mudah percaya vs Pencuriga
10 . Praktis vs Imajinatif
11 . Blak-blakan vs Tersembunyi
12 . Percaya diri vs Mudah cemas
13 . Konservatif vs Suka mencoba
14 . Tergantung pada kelompok vs Mandiri
15 . Tidak terkendali vs Terkendali
16 . Rileks vs Tegang
4. FAKTOR-FAKTOR TERBENTUKNYA PERILAKU ORGANISASI
A. SIKAP
sikap adalah gambaran kepribadian seseorang yang terlahir melalui gerakan fisik dan tanggapan pikiran terhadap suatu keadaan atau suatu objek. Berkowitz, dalam Azwar (2000:5) menerangkan sikap seseorang pada suatu objek adalah perasaan atau emosi, dan faktor kedua adalah reaksi/respon atau kecenderungan untuk bereaksi. Sebagai reaksi maka sikap selalu berhubungan dengan dua alternatif, yaitu senang (like) atau tidak senang (dislike), menurut dan melaksanakan atau menjauhi/menghindari sesuatu.
Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa sikap adalah kecenderungan, pandangan, pendapat atau pendirian seseorang untuk menilai suatu objek atau persoalan dan bertindak sesuai dengan penilaiannya dengan menyadari perasaan positif dan negatif dalam menghadapi suatu objek.
Katz (dalam Walgito, 1990:110) menjelaskan bahwa sikap itu mempunyai empat fungsi, yaitu:
1. Fungsi instrumental atau fungsi penyesuaian, atau fungsi manfaat.
Fungsi ini berkaitan dengan sarana tujuan. Di sini sikap merupakan sarana untuk mencapai tujuan. Orang memandang sampai sejauh mana objek sikap dapat digunakan sebagai sarana dalam mencapai tujuan. Bila objek sikap dapat membantu seseorang dalam mencapai tujuannya, maka orang akan bersikap positif terhadap objek sikap tersebut.
2. Fungsi pertahanan ego
Ini merupakan sikap yang diambil oleh seseorang demi untuk mempertahankan ego atau akunya. Sikap diambil seseorang pada waktu orang yang bersangkutan terancam dalam keadaan dirinya atau egonya, maka dalam keadaan terdesak sikapnya dapat berfungsi sebagai mekanisme pertahanan ego.
3. Fungsi ekspresi nilai
Sikap yang ada pada diri seseorang merupakan jalan bagi individu untuk mengekspresikan nilai yang ada dalam dirinya. Dengan mengekspresikan diri seseorang akan mendapatkan kepuasan dan dapat menunjukkan keadaan dirinya. Dengan mengambil nilai sikap tertentu, akan dapat menggambarkan sistem nilai yang ada pada individu yang bersangkutan.
4. Fungsi pengetahuan
Fungsi ini mempunyai arti bahwa setiap individu mempunyai dorongan untuk ingin tahu. Dengan pengalamannya yang tidak konsisten dengan apa yang diketahui oleh individu, akan disusun kembali atau diubah sedemikian rupa sehingga menjadi konsisten. Ini berarti bila seseorang mempunyai sikap tertentu terhadap suatu objek, menunjukkan tentang pengetahuan orang tersebut objek sikap yang bersangkutan.
Pengalaman di tempat kerja :
Kemampuan Sikap seorang guru, dalam menghadapi kepala sekolah, sesama guru, anak didik, menghadapi orang tua dan karyawan lain di lingkungan sekolah.
B. PERSEPSI
Persepsi, menurut Rakhmat Jalaludin (1998: 51), adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.
Menurut Ruch (1967: 300), persepsi adalah suatu proses tentang petunjukpetunjuk inderawi (sensory) dan pengalaman masa lampau yang relevan diorganisasikan untuk memberikan kepada kita gambaran yang terstruktur dan bermakna pada suatu situasi tertentu.
Senada dengan hal tersebut Atkinson dan Hilgard mengemukakan bahwa persepsi adalah proses dimana kita menafsirkan dan mengorganisasikan pola stimulus dalam lingkungan. Gibson dan Donely menjelaskan bahwa persepsi adalah proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh seorang individu.
Proses pembentukan persepsi dijelaskan oleh Feigi (dalam Yusuf, 1991: 108) sebagai pemaknaan hasil pengamatan yang diawali dengan adanya stimuli. Setelah mendapat stimuli, pada tahap selanjutnya terjadi seleksi yang berinteraksi dengan "interpretation", begitu juga berinteraksi dengan "closure". Proses seleksi terjadi pada saat seseorang memperoleh informasi, maka akan berlangsung proses penyeleksian pesan tentang mana pesan yang dianggap penting dan tidak penting. Proses closure terjadi ketika hasil seleksi tersebut akan disusun menjadi satu kesatuan yang berurutan dan bermakna, sedangkan interpretasi berlangsung ketika yang bersangkutan memberi tafsiran atau makna terhadap informasi tersebut secara menyeluruh.
Persepsi meliputi juga kognisi (pengetahuan), yang mencakup penafsiran objek, tanda dan orang dari sudut pengalaman yang bersangkutan. Selaras dengan pernyataan tersebut Krech, dkk, mengemukakan bahwa persepsi seseorang ditentukan oleh dua faktor utama, yakni pengalaman masa lalu dan faktor pribadi.
Pengalaman di tempat kerja :
Kemampuan Sikap seorang guru, dalam menafsirkan gejala dan sikap dari lingkungan di sekolah, terutama respon anak didik dari caranya mengajar atau berkomunikasi dengan mereka.
C. MOTIVASI
Motivasi adalah faktor yang mendorong orang untuk bertindak dengan cara tertentu. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa motivasi pada dasarnya adalah kondisi mental yang mendorong dilakukannya suatu tindakan (action atau activities) dan memberikan kekuatan (energy) yang mengarah kepada pencapaian kebutuhan, memberi kepuasan ataupun mengurangi ketidakseimbangan. Oleh karena itu tidak akan ada motivasi, jika tidak dirasakan rangsangan-rangsangan terhadap hal semacam di atas yang akan menumbuhkan motivasi, dan motivasi yang telah tumbuh memang dapat menjadikan motor dan dorongan untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan atau pencapaian keseimbangan.
Motivasi adalah dorongan untuk mencapai tujuan tertentu. Dorongan itu bisa saja berbentuk: antusiasme, harapan dan semangat. Semua yang kita lakukan setiap hari senantiasa dibayangi oleh adanya motivasi. Misalnya, seorang karyawan yang bekerja tentu saja memiliki motivasi bekerja, begitu pula seorang atlet memiliki motivasi bertanding, seorang pelajar dengan motivasi belajar, dan lain sebagainya.
Motivasi ibarat api di dalam pikiran seseorang yang terkadang besar membara kadang juga redup, tergantung kondisi mentalnya. Jika seseorang ingin menggapai kesuksesan, motivasi adalah panas api yang harus dijaga jangan sampai padam, karena padamnya motivasi berarti kehilangan bahan bakar untuk menggerakkan mesin tubuh ini untuk menggapai tujuan. Memberikan motivasi adalah menyalakan kembali api motivasi di dalam diri seseorang supaya kembali bersemangat, memiliki keberanian dan pantang menyerah untuk melakukan sesuatu dengan cara tertentu. Kemampuan untuk memberikan motivasi adalah adalah sebuah keterampilan yang bisa dipelajari oleh siapa saja, seorang ibu rumah tangga, mahasiswa, manajer, dan tentu saja pemimpin.
Memotivasi diri sendiri adalah hal yang pokok sebelum kita memotivasi orang lain. Kita harus menciptakan suasana dan keteladanan yang dapat menjadi bahan bakar kita untuk mulai membakar orang lain. Para motivator ulung adalah orang-orang yang dihormati atas keberhasilan mereka sebelumnya.
Di dalam bukunya Successful Motivation in a week, Harvey memberikan pelajaran selama seminggu belajar motivasi diri sendiri dan orang lain secara praktikal. Harvey menyebutkan bahwa calon-calon motivator memiliki sifat-sifat sebagai berikut:
• Positif
• Rasa berterima kasih kepada orang-orang terbaik yang bekerja bersama kita
• Menyadari pentingnya harga diri
Pengalaman di tempat kerja :
Kemampuan seorang guru untuk memotivasi diri sendiri untuk meningkatkan cara mengajar, memotivasi anak didik untuk semangat belajar dan memotivasi sesama guru untuk bahu membahu bekerjasama meningkatkan kualitas belajar mengajar di sekolah.
D. STRESS
Stres itu dimulai dari rasa tidak puas terhadap semua hal yang sedang Anda hadapi dalam hidup Anda ini. Seharusnya Anda menyadari bahwa hidup itu tidak sempurna, dan untuk itu Anda harus memperbaiki ketidaksempurnaan hidup ini dengan pikiran positif. Jangan biarkan hidup Anda dikendalikan oleh nafsu dan hasrat keinginan yang tidak terdefinisi secara jelas. Anda harus memastikan bahwa Anda sangat mengenal dan mengerti tentang semua keinginan hidup Anda. Bila Anda tidak memiliki dasar pijakan hidup yang kuat, maka stres dengan mudah bisa menghancurkan semua mimpi dan cita - cita Anda. Stres itu kapan saja bisa hadir dalam hidup Anda, walaupun Anda tidak pernah mengundangnya untuk datang dalam kehidupan Anda. Tetapi bagi stres, setiap kelemahan dan kelengahan adalah lahan subur untuk tumbuh dan berkembang dengan subur. Anda harus selalu menyiapkan diri Anda sebaik mungkin, agar stres tidak menjadikan diri Anda sebagai tempatnya untuk tumbuh dan berkembang biak.
Sebagai manusia tidaklah mudah untuk hidup dalam pikiran positif yang utuh dan penuh, sebab seribu godaan dan cobaan selalu akan hadir dalam sepanjang hidup Anda, yang mencoba mempengaruhi Anda untuk tidak hidup dalam pikiran positif.
Kebiasaan manusia adalah lebih senang menyebarluaskan berita negatif, dan Anda bisa menyaksikan dan mendengarkan berbagai berita negatif yang menghiasi wajah media masa. Setiap orang dipaksa setiap hari untuk mengisi otak bawah sadarnya dengan pikiran negatif tanpa dia inginkan. Semuanya berproses secara otomatis, dan inilah sumber utama dari stres.
Stres adalah buah dari pikiran negatif. Dan, semua ini dihasilkan dari pola pikir yang selalu lebih menonjolkan sisi buruk dari kehidupan. Mungkin bagi banyak orang dengan membicarakan kekurangan dan kelemahan dari orang lain terasa seperti sebuah sensasi hidup yang mengembirakan, tapi tanpa mereka sadari, mereka telah mengisi pikiran mereka sendiri dengan kata - kata negatif, yang nantinya akan menjadi penyumbang terbesar buat stres yang menyerang diri mereka. Tantangan hidup kita di bumi ini adalah cara kita mengendalikan diri untuk bisa menjalani hidup dalam sebuah keseimbangan yang diisi dengan nilai - nilai kebaikan.
Pengalaman di tempat kerja :
Kemampuan seorang guru untuk mengendalikan emosi dan kejiwaan, sehingga tidak mengalami stress akibat lingkungan di tempat dia mengajar, terutama menghadapi tingkah laku dan sikap anak didik yang mungkin di luar batas-batas normal, sehingga menciptakan kondisi proses belajar mengajar yang kurang menyenangkan.
5. MODEL PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI SEKOLAH
Salah satu masalah pendidikan yang kita hadapi dewasa ini adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan, antara lain memlalui berbagai pelatihan dan peningkatan kualifikasi guru, penyediaan dan perbaikan sarana/prasarana pendidikan, serta peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang merata. Sebagaian sekolah, terutama di kota-kota, menunjukkan peningkatan mutu yang cukup menggembirakan, namun Sebagian lainnya masih memprihatinkan. Dari berbagai pengamatan dan analisis, sedikitnya ada tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata.
Pertama, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan educational production function yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. Pendekatan ini melihat bahwa lembaga pendidikan berfungsi sebagai pusat produksi yang apabila dipilih semua input (masukan) yang diperlukan dalam kegiatan produksi tersebut, maka lembaga ini akan menghasilkan output yang dikehendaki. Dalam kenyataan, mutu pendidikan yang diharapkan tidak terjadi, mengapa? Karena selama ini dalam menerapkan pendekatan education production function terlalu memusatkan pada input pendidikan dan kurang memperhatikan pada proses pendidikan. Padahal, proses pendidikan sangat menentukan output pendidikan.
Kedua, penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara sentralistik, sehingga sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi, yang kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat. Dengan demikian sekolah kehilangan kemandirian, motivasi, dan inisiatif untuk mengembangkan dan memajukan lembaganya termasuk peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional.
Ketiga, peran serta masyarakat, khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat minim. Partisipasi masyarakat pada umumnya selama ini lebih banyak bersifat dukungan dana, bukan pada proses pendidikan (pengambilan keputusan, monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas). Berkaitan dengan akunfabilitas, sekolah tidak mempunyai beban untuk mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pendidikan kepada masyarakat, khususnya orang tua siswa, sebagai salah satu pihak utama yang berkepentingan dengan pendidikan.
Berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan, salah satunya yang sekarang sedang dikembangkan adalah reorientasi penyelenggaraan pendidikan, melalui manajemen sekolah (School Based Management).
Manajemen berbasis sekolah atau School Based Management dapat didefinisikan dan penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengembilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan mutu sekolah dalam pendidikan nasional.
Esensi dari MBS adalah otonomi dan pengambilan keputusan partisipasi untuk mencapai sasaran mutu sekolah. Otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan (kemandirian) yaitu kemandirian dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Jadi, otonomi sekolah adalah kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku. Kemandirian yang-dimaksud harus didukung oleh sejumlah kemampuan, yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan yang terbaik, kemampuan berdemokrasi/menghargai perbedaan pendapat, kemampuan memobilisasi sumber daya, kemampuan memilih cara pelaksanaan yang terbaik, kemampuan berkomunikasi dengan cara yang efektif, kemampuan memecahkan persoalan-persoalan sekolah, kemampuan adaftif dan antisipatif, kemampuan bersinergi danm berkaborasi, dan kemampuan memenuhi kebutuhan sendiri.
Pengambilan keputusan partisipatif adalah suatu cara untuk mengambil keputusan melalui penciptaan lingkungan yang terbuka dan demokratik, di mana warga sekolah (guru, karyawan, siswa,orang tua, tokoh masyarakat) dkjorong untuk terlibatsecara langsung dalam proses pengambilankeputusan yang akan dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan sekolah.
Pengambilan keputusan partisipasi berangkat dari asumsi bahwa jika seseorang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan tersebut, sehingga yang bersangkutan akan merasa memiliki keputusan tersebut, sehingga yang bersangkutan akan bertanggung jawab dan berdedikasi sepenuhnya untuk mencapai tujuan sekolah. Singkatnya makin besar tingkat partisipasi, makin besar pula rasa memiliki, makin besar rasa memiliki, makin besar pula rasa tanggung jawab, dan makin besar rasa tanggung jawab makin besar pula dedikasinya.
Sekolah di Indonesia pasti pernah diajari berkali-kali bagaimana cara pengambilan keputusan melalui musyawarah dan mufakat adalah ciri khas Indonesia. Tentunya cara ini bukanlah satu-satunya cara mengambil keputusan secara kolektif. Misalnya ada cara voting, baik independen (kita tidak bisa melihat pilihan orang lain) atau dependen (setiap orang bisa melihat pilihan orang lain, sehingga pilihan seseorang bisa terpengaruh pilihan orang lain).
Saya yakin setiap cara pengambilan keputusan memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung pada jenis masalah yang dihadapi. Nah, sepertinya menarik untuk mengetahui dalam situatu seperti apa pengambilan keputusan dengan cara voting independen, non-independen dan konsensus menjadi superior.
Kita bisa rancang sebuah eksperimen dimana orang diminta untuk menyelesaikan sebuah masalah. Lalu kita buat tiga kelompok yang masing-masing menggunakan cara pengambilan keputusan yang berbeda, yaitu:
• Voting
Voting adalah memilih calon dari kandidat-kandidat yang ada oleh orang-orang yang memiliki hak ikut serta dalam voting. Yang memiliki hak suara voting memilih kandidat yang dijagokan, dan hasilnya dihitung. Kandidat yang mendapat suara voting tertinggi dialah yang layak manjadi pemenangnya. Contoh : pemilu, pilkada, memilih ketua kelas, dll.
• Konsensus (musyawarah/kesepakatan)
Musyawarah adalah cara efektif melahirkan kemenangan bersama, cara paling bijak untuk menyelesaikan masalah dan cara tepat untuk bersinergi. Setidaknya, ada sembilan resep musyawarah yang bisa kita jalankan. Ke-9 resep itu adalah:
[1]. Sadar realitas.
[2]. Niat dan tekadkan musyawarah sebagai sarana mencari solusi terbaik.
[3]. Berani duduk bersama.
[4]. Miliki keterampilan mendengarkan.
[5]. Miliki keterampilan menjelaskan.
[6]. Miliki keberanian untuk mengambil sisi-sisi kebenaran dari alasan orang lain.
[7]. Berani menurunkan keinginan ideal untuk mendapatkan posisi ideal bersama. Prinsip win win solution menjadi kata kunci.
[8].Bila kesepakan telah dicapai, berusahalah seoptimal mungkin untuk komitmen.
[9]. Semua kesepakatan hanya boleh dilakukan dijalan Allah.
• Cara Undian
Seperti yang kita tahu, undian mirip dengan arisan ibu-ibu dengan mengocok nama-nama kandidat dan nama yang dikeluar setelah di dikocok adalah pemenangnya. Contoh : arisan, undian kartu pos, dan lain-lain.
6. LINGKUNGAN SEKOLAH
Lingkungan merupakan tempat tinggal komunitas tertentu. Sebagai tempat tinggal, lingkungan akan dirawat oleh yang bertempat tinggal sesuai dengan karakternya masing-masing. Oleh karena itu dengan nyata kita dapat membedakan antara lingkungan perumahan elite, lingkungan kampung, lingkungan nelayan, lingkungan rumah kolong, dll. Selain dikarenakan oleh penghuni, lingkungan juga dapat diwarnai oleh fungsi, misalnya prabrik kimia, rumah sakit, apotik, dll. Namun demikian walau fungsi lingkungan sama, tetapi karakteristik penghuni berbeda akan mempengaruhi pula penataan lingkungan. Dari lingkungan kita dapat meneropong karakter / tabiat penghuninya.
Lingkungan sekolah merupakan indikator karakter civitas sekolah maupun kualitas sekolah secara keseluruhan. Sekolah merupakan lingkungan yang dialami oleh anak setiap hari. Lingkungan ini merupakan produk perancangan arsitektur yang dibuat oleh orang dewasa untuk anak. Dalam rangka mendukung pendekatan perancangan yang berorientasi pada kebutuhan pemakai (user-oriented), penelitian ini bermaksud mengungkapkan persepsi anak terhadap lingkungan sekolah melalui analisis gambaran visual tentang lingkungan sekolah yang selama ini dialaminya dan lingkungan sekolah yang diinginkannya. Hasil penelitian ini menunjukkan beragam cara pandang yang digambarkan oleh anak, yang dapat menjadi masukan berharga bagi proses perancangan lingkungan yang berorientasi pada kebutuhan anak.
Lingkungan keluarga yang kondusif bagi pembentukan sifat individu berprestasi tinggi adalah lingkungan Yang menerapkan pola asuh yang otoritatif. Lingkungan sekolah yang kondusif bagi pembentukan sifat individu berprestasi tinggi adalah lingkungan
Sekolah yang menerapkan pola bina yang otoritatif. Ada alur pembentukkan individu berprestasi tingkat 0 yakni diawali dengan pola asuh dan pola bina yang Otoritatif yang keduanya akan berpengaruh terhadap pembentukkan sifat, dan pada akhirnya akan Mempengaruhi prestasi individu.
Dunia pendidikan saat ini sudah berkembang begitu pesatnya dari waktu ke waktu. Pendidikan saat ini memang sudah sangat jauh berbeda dengan pendidikan di masa lalu. Perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan sudah sangat pesat sehingga sangat mempengaruhi dunia pendidikan saat ini. Lembaga pendidikan mulai banyak mermunculan sehingga tidak bisa dielakkan akan terjadi persaingan yang sangat ketat diantara lembaga-lembaga pendidikan itu.Lembaga pendidikan mempunyai tanggung jawab sosial yang sangat besar kepada bangsa ini bukan hanya sekedar untuk kepentingan bisnis semata. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi dunia pendidikan diantaranya adalah kepemimpinan seorang kepala sekolah. Seorang kepala sekolah adalah seorang pemimpin yang akan menentukan langkah-langkah pendidikan yang efektif di lingkungan sekolah.
Kepemimpinan seorang kepala sekolah sedikit banyak dapat mempengaruhi pendidikan di lingkungan sekolah. Sekolah juga membutuhkan figur seorang pemimpin yang siap bekerja keras untuk dapat memajukan sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan sekolah yang dipimpinnya. Faktor lain yang berperan mempengaruhi pendidikan adalah kinerja guru yang berkualitas. Seorang guru dituntut untuk dapat memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pendidikan di lingkungan sekolah terutama dalam hal belajar
Komponen pendidikan yang tidak kalah pentingnya adalah sarana dan prasarana yang mendukung. Mulai dari bangunan fisik, ruang kelas, taman, perpustakaan, laboratorium, sarana olah raga dan kesenian, arena bermain, kantin, perlengkapan kelas, sampai dengan alat peraga edukasi yang dimiliki. Seiring dengan kemajuan bidang informasi dan teknologi, nampaknya bukan hal yang baru sebuah sekolah memiliki fasilitas akses jaringan internet dan website sendiri, dimana setiap stake holders dapat berinteraksi dan berkomunikasi di dunia maya.
Hal ini, akan sangat membantu bagi orang tua untuk memantau perkembangan putra-putrinya secara cepat tanpa harus secara fisik datang kesekolah. Dengan didukung sarana dan prasarana yang baik, diharapkan semua peserta didik dapat belajar secara enjoy, nyaman, dan betah. Sekolah diibaratkan sebagai rumah kedua bagi anak-anak, sehingga sekolah yang baik mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan siswa. Hal yang perlu diperhatikan juga mengenai rasio jumlah siswa dengan luas ruangan kelas serta fasilitas pembelajaran yang lain.
Lokasi sekolah dan lingkungan.
Lokasi yang dimaksud dapat dipandang dari jarak sekolah ke rumah, lingkungan sekitar dan sarana transportasinya. Bisa dibayangkan seorang anak harus bangun pagi-pagi sekali karena letak sekolahnya jauh. Tentu ia pulang dalam keadaan lelah karena jarak yang ditempuhnya memakan waktu yang lama. Belum lagi jika terjadi kemacetan lalu lintas, bisa dimungkinkan sering terlambat pulang maupun masuk sekolahnya.
Lalu kapan ia bisa belajar di rumah dengan nyaman? Bagaimana ia bisa mengembangkan interaksi dengan anggota keluarga lain di rumahnya? Maka, faktor lokasi dan lingkungan ini hendaknya diperhatikan oleh orang tua dan anak itu sendiri dalam menentukan sekolah pilihannya. Perlu dipikirkan juga mengenai sekolah yang berlokasi di pusat perkotaan atau keramaian dan yang berada di pinggiran atau lebih dekat dengan suasana alam, semua memiliki plus-minus-nya.
Dengan Lingkungan sekolah yang menunjang sarana dan prasarananya, diharapkan :
1. Tercapainya kelulusan 100% dengan nilai yang kompetitif
2. Terciptanya suasana belajar yang kondusif dan interaktif.
3. Terciptanya suasana lingkungan sekolah yang agamis dan berwawasan iptek.
4. Tercapainya posisi atas pada ajang kompetisi bidang akademis dan non akademis pada tingkat kabupaten.
5. Terwujudnya suasana kekeluargaan yang kooperatif antarwarga sekolah dan lingkungan sekolah.
6. Terwujudnya partisipasi aktif warga sekolah dan lingkungan sekolah dalam kerangka kegiatan pengembangan dan kemajuan sekolah.
7. Terwujudnya warga sekolah yang tanggap terhadap perkembangan teknologi
7. STRATEGI PERUBAHAN BUDAYA DAN IKLIM SEKOLAH
Budaya sekolah Menurut Deal dan Peterson (1999), budaya sekolah adalah sekumpulan nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol yang dipraktikkan oleh kepala sekolah, guru, petugas administrasi, siswa, dan masyarakat sekitar sekolah.
Budaya sekolah adalah satu elemen sekolah yang teramat penting dan nyata, tetapi sangat sulit untuk mendefinisikannya. Pemahaman terhadap budaya sekolah merupakan salah satu faktor penting dalam struktur reformasi dan kebijakan pendidikan di mana pun. Karena, apa pun jenis perubahan yang diinginkan dalam suatu sistem pendidikan pasti akan mengalami resistensi. Karena itu perlu dilakukan pendefinisian yang bijak tentang budaya sekolah, serta sejauh mana para pengambil kebijakan dan pelaksana sekolah memahami makna budaya sekolah dalam konteks peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.
Pepatah tua dari para antropolog mengatakan, ikan adalah makhluk terakhir yang masuk ke air (Kluckholn, 1949), meskipun ikan hampir dipastikan akan selalu berada di dalam air. Begitu juga budaya sekolah (school culture) dan proses belajar-mengajar, seperti air dan ikan, adalah sebuah keniscayaan dan takdir yang tidak bisa dipisahkan karena keduanya merupakan entitas yang berbeda. Keduanya memberi arti banyak dalam menentukan perspektif dan ragam tindakan pengajaran. Guru dalam konteks budaya dapat memengaruhi setiap aspek dari proses belajar-mengajar (Peterson, 1998). Karena itu, penting dikemukakan hal-hal yang berkaitan dengan budaya sekolah, seperti definisi, efek budaya sekolah terhadap keseluruhan performansi guru dan siswa, dan implikasinya terhadap kebijakan UN dalam konteks budaya sekolah.
Menemukan budaya sekolah
Bayangkan Anda memasuki sebuah sekolah, hal apa kira-kira yang akan Anda lihat dan dengar? Sulit atau mudah memasuki lingkungan sekolah tersebut. Bagaimana cara guru dan siswa menyapa Anda. Bagaimana dengan pengaturan ruang administrasi dan papan demo keterampilan siswa ditata dan ditampilkan, serta ruang kelas dibentuk. Bagaimana suasana belajar-mengajar berlangsung, dan yang tidak kalah pentingnya, bagaimana kondisi kamar kecil (toilet) sekolah. Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan budaya. Sebab, sekolah sedang berusaha memberikan impresi terhadap tamu dan pengunjung lainnya bahwa inilah kami, inilah budaya sekolah kami.
Jika budaya kita definisikan sebagai seperangkat norma, nilai, kepercayaan, dan tradisi yang berlangsung dari waktu ke waktu, budaya sekolah adalah satu set ekspektasi dan asumsi dari norma, nilai, dan tradisi yang secara diam-diam mengarahkan seluruh aktivitas personel sekolah (Peterson, 1998). Karena budaya sekolah bukan suatu entitas statis, maka proses pembentukan norma, nilai, dan tradisi sekolah akan terus berlangsung melalui interaksi dan refleksi terhadap kehidupan dan dunia secara umum (Finnan, 2000). Dalam bahasa Hollins (1996), sebagai agen perubahan, 'sekolah dibentuk oleh praktik dan nilai budaya serta merefleksikan norma-norma dari masyarakat saat mereka masih sedang dikembangkan'. Atau, seperti hidrogen yang merupakan elemen utama air, maka nilai-nilai dalam masyarakat juga merupakan bagian utama dari budaya sekolah.
Tata kelola dan kepemimpinan (leadership) dari pengelola pendidikan dan sekolah juga dapat membentuk budaya sekolah. Dalam konteks ini, kebijakan yang dibuat oleh otoritas pendidikan secara langsung juga dapat memengaruhi budaya sekolah yang sedang dan akan berlangsung. Birokrasi, dengan demikian, dapat menjadi penghambat dan sekaligus stimulus yang konstruktif terhadap keberlangsungan sebuah budaya sekolah yang ingin dan akan dikembangkan oleh komunitas sekolah (Goodlad, 1984; Donahoe, 1997; McLaren, 1999).
Efek budaya sekolah
Budaya dari setiap sekolah bisa jadi memiliki efek positif terhadap proses belajar-mengajar atau sebaliknya memiliki efek negatif serta menghalangi berfungsinya sebuah sekolah. Hanson dan Childs (1998) menggambarkan sekolah dengan suatu iklim sekolah yang positif sebagai 'suatu wadah tempat siswa dan guru saling berbagi dan mereka menggunakan ketulusan hati dalam proses belajar'.
Jika norma-norma dasar pembelajaran seperti pertemanan, kegembiraan dalam proses belajar yang menyenangkan (fun and enjoy learning), manajemen yang terbuka, aturan yang ditegakkan, serta visi-misi sekolah yang terdistribusi dengan baik dalam segenap benak komunitas sekolah, maka sekolah tersebut dapat dikatakan memiliki ciri-ciri budaya sekolah yang positif. Sebaliknya, sebuah sekolah dapat dicirikan memiliki budaya sekolah yang negatif jika tidak memiliki indikator tadi serta adanya penolakan dari guru dan manajemen sekolah untuk melakukan praktik pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan dasar siswa; diayomi dan dilayani sesuai bakat dan minatnya (Peterson dan Deal, 1998).
Terlepas dari apakah positif atau negatif sebuah budaya sekolah, pengenalan terhadap 'perubahan budaya belajar' guru dan siswa harus terus menjadi perhatian seluruh komunitas sekolah. Menurut Sarason (1996), adalah sulit untuk menentukan sifat alami suatu budaya karena kita sendiri memiliki nilai dan tradisi serta kebiasaan yang selalu terbawa ke dalam budaya sekolah. Karena itu, cara pandang kita terhadap nilai-nilai keagamaan, tradisi, kebijakan otoritas pendidikan, kurikulum, dan metodologi pengajaran akan menempati setiap ruang dan relung pikiran siswa dalam proses belajar. Bentuk perubahan apa pun yang akan datang dan ditawarkan kepada komunitas sekolah akan selalu mendapatkan perlawanan dari guru dan siswa, secara tersembunyi maupun terang-terangan. Contoh paling gamblang bagaimana budaya sekolah berlaku dan diterapkan si sekolah-sekolah kita dapat dilihat dari bagaimana sekolah 'memosisikan' diri mereka terhadap kebijakan ujian nasional yang sedang diselenggarakan pemerintah saat ini. Garis dasar untuk perubahan sekolah adalah bahwa supaya perubahan apa pun yang akan datang dan diusulkan otoritas pendidikan harus disesuaikan dengan budaya sekolah.
KONSEP Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) ditengarai banyak pihak sebagai cara mutakhir peningkatan mutu pendidikan di Tanah Air. MBS pada dasarnya merupakan pendelegasian otoritas pengambilan keputusan untuk mengelola sumber daya keuangan, kurikulum, serta profesionalisme guru ke tingkat sekolah. Artinya, segala keputusan yang menyangkut pengelolaan sekolah sedapat mungkin diputuskan oleh pihak terkait dalam lingkungan sekolah, seperti kepala sekolah, guru, orang tua murid, dan tokoh masyarakat setempat yang tergabung dalam dewan sekolah.
Menurut Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, MBS sedang dan telah diujicobakan di 1.000 sekolah. Dari beberapa laporan awal diketahui bahwa dalam penerapannya ternyata konsep ini masih belum menunjukkan hasil yang sepenuhnya memuaskan.
Di satu pihak, sejumlah sekolah yang menerapkan MBS telah mampu mewujudkan proses belajar yang aktif, efektif, dan menyenangkan. MBS berhasil menggalang partisipasi aktif masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan dan transparansi manajemen sekolah.
Di pihak lain, MBS masih belum menyentuh perubahan mendasar dalam meningkatkan sistem pengelolaan pendidikan partisipatif`. Penyebabnya, antara lain, karena lemahnya kepemimpinan kepala sekolah, kurang profesionalnya guru, serta sikap apatis masyarakat.
Dari perspektif sosiologis, kegagalan penerapan MBS bermuara dari tidak adanya perubahan budaya sekolah (school culture), yakni berubahnya semangat, sikap, dan perilaku pihak-pihak yang terkait dengan sekolah. Karenanya, penerapan MBS mensyaratkan tidak hanya perubahan kebijakan legal dan formal, melainkan pula perubahan nilai, semangat, sikap, dan perilaku para aktor sekolah seperti kepala sekolah, guru, orang tua murid, dan siswa.
Penerapan MBS memerlukan perubahan budaya sekolah dari budaya konservatif yang pasif dan sentralistik menjadi budaya inovatif yang egaliter, aktif, dan dinamis. Budaya sekolah Menurut Deal dan Peterson (1999), budaya sekolah adalah sekumpulan nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol yang dipraktikkan oleh kepala sekolah, guru, petugas administrasi, siswa, dan masyarakat sekitar sekolah.
Budaya sekolah merupakan ciri khas, karakter, dan citra sekolah tersebut di masyarakat luas. Untuk mengenali budaya sekolah, cobalah masuk ke sekolah favorit dan sekolah yang mutunya kurang baik (negeri atau swasta).
Perhatikan bagaimana proses belajar-mengajar, disiplin, dan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah tersebut. Kemudian, bandingkan situasi dan kondisi antara dua sekolah tadi. Niscaya akan dirasakan suasana, iklim dan kebiasaan yang sangat berbeda. Suasana, iklim, dan kebiasaan itulah yang dinamakan budaya sekolah.
Menurut Sergiovanni (1999), budaya sekolah memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap suatu proses perubahan berencana (planned change). Karenanya, dalam konteks penerapan MBS, Sergiovanni menyarankan agar para pengambil kebijakan, para penilik, dan kepala sekolah menggunakan pendekatan budaya sekolah atau school culture approach.
Alasannya:
Pertama, pendekatan budaya lebih menitikberatkan faktor manusia di atas faktor-faktor lainnya. Peran manusia amat sentral dalam suatu proses perubahan berencana. Sesuai dengan pepatah man behind the gun, manusia adalah faktor yang menentukan keberhasilan perubahan, bukan struktur atau peraturan legal.
Kedua, pendekatan budaya menekankan pentingnya peran nilai dan keyakinan dalam diri manusia. Aspek ini merupakan elemen yang sangat berpengaruh dalam membentuk sikap dan perilaku. Karenanya, pendekatan budaya menomorsatukan transformasi nilai dan keyakinan terlebih dahulu sebelum perubahan yang bersifat legal-formal.
Ketiga, pendekatan budaya memberikan penghormatan dan penerimaan terhadap perbedaan-perbedaan yang ada. Sikap menerima dan saling hormat akan menciptakan rasa saling percaya dan kebersamaan di antara anggota organisasi. Rasa kebersamaan akan memunculkan kerja sama, dan kerja sama akan mewujudkan sikap profesionalisme.
Strategi perubahan
Strategi perubahan budaya sekolah, kata Deal dan Kennedy (1985), meniscayakan perubahan dalam tiga tataran: yaitu tataran nilai yang dianut, tataran praktik keseharian, dan tataran simbol-simbol budaya.
Dalam tataran nilai, perubahan yang harus dilakukan adalah mengubah nilai-nilai lama yang menghambat dengan nilai baru yang mendukung MBS. Nilai lama yang bercirikan nilai sedang-sedang saja (mediocre values), seperti berpuas diri, tertutup, pasif, dan ketergantungan, harus diubah menjadi nilai baru yang bercirikan nilai keunggulan (excellent values), seperti terbuka terhadap innovasi, kompetitif, berinisiatif, independen, dan bertanggung jawab.
Internalisasi nilai keunggulan ini sangat penting bagi keberhasilan MBS. Tanpa adanya semangat untuk berinovasi, berkompetisi, dan berani menanggung risiko, pelaksanaan MBS hanya akan berjalan di tempat. Tanpa dukungan nilai keunggulan, MBS tidak akan menghasilkan perubahan apa-apa pada kualitas pendidikan di sekolah.
Dalam tataran praktek keseharian, transformasi yang harus dilakukan adalah mengubah sikap dan perilaku lama yang bercirikan `asal-asalan` (asal mengajar, asal datang, dan asal jadi), menjadi sikap dan perilaku baru yang bercirikan kesungguhan dan dedikasi.
Perilaku lama yang cenderung menunggu petunjuk dan berorientasi ke atasan juga direformasi menjadi perilaku baru yang penuh inisiatif dan berorientasi kepada proses belajar siswa.
Perubahan ini dapat diwujudkan melalui tiga hal: pertama, pensosialisasian visi dan misi sekolah sebagai tujuan ideal yang ingin dicapai pada masa mendatang. Kedua, penetapan rencana strategis mingguan atau bulanan sebagai tahapan dan langkah sistematis yang akan dilakukan oleh semua pihak di sekolah. Ketiga, pemberian penghargaan terhadap prestasi guru dan siswa sebagai usaha pembiasaan (habit formation) yang menjunjung sikap dan perilaku yang profesional. Penghargaan dapat berwujud materi maupun nonmateri, seperti ucapan selamat atas prestasi tertentu.
Dalam tataran simbol-simbol budaya, perubahan yang harus dilakukan adalah mengganti simbol budaya yang konservatif dan sentralistik dengan simbol budaya yang dinamis.
Perubahan simbol dapat dilakukan dengan mengubah penataan kelas dan ruang guru, serta pemasangan hasil karya siswa, foto-foto, dan moto. Misalnya, penataan tempat duduk siswa yang berpusat pada guru harus diubah menjadi tempat duduk yang mendorong interaksi antarsiswa sehingga mereka dapat belajar dengan aktif, kreatif, dan menyenangkan. Hasil karya siswa yang berupa gambar, karangan, puisi, dan kerajinan harus dipasang di ruangan kelas untuk mendorong kebanggaan berprestasi. Foto-foto ilmuwan serta karya-karyanya perlu juga perlu dipajang guna merangsang motivasi belajar siswa.
Adalah kurang tepat, untuk tidak mengatakan naif, jika penerapan MBS hanya dilakukan dengan mengubah struktur organisasi atau membentuk dewan sekolah. Pendekatan budaya sekolah sangat diperlukan dalam penerapan MBS. Pelaksanaan MBS meniscayakan proses perubahan pada nilai, semangat, sikap, dan perilaku semua komponen sekolah.
Kepala sekolah dituntut untuk menjadi pemimpin yang proaktif dan berwawasan. Para guru diharapkan bersikap kreatif untuk menggali metode mengajar yang kreatif. Masyarakat dianjurkan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pendidikan di sekolah. Diibaratkan dengan bercocok tanam, MBS adalah bibit unggul tahan hama, sedangkan budaya sekolah adalah sebidang tanah yang akan ditanami. Seunggul dan sebagus apa pun bibit yang akan ditanam, ia tidak akan tumbuh subur jika tanahnya tetap gersang penuh alang-alang.
Budaya sekolah (school culture), itulah kata kunci yang tidak mendapat perhatian secara sungguh-sungguh dari para pengelola pendidikan kita. Budaya sekolah perlu dibangun berdasarkan kekuatan karakteristik budaya lokal masyarakat tempat sekolah itu berada. Budaya sekolah adalah detak jantung sekolah itu sendiri, perumusannya harus dilakukan dengan sebuah komitmen yang jelas dan terukur oleh komunitas sekolah yakni guru, siswa, manajemen sekolah, dan masyarakat.
Sejauh ini strategi perubahan budaya dan iklim sekolah di tempat saya bertugas, tidak mengalami perkembangan yang signifikan, dimana adanya program pemerintah tentang MBS, belum direspon secara menyeluruh, dalam arti hanya faktor-faktor tertentu saja yang sudah diterapkan, tapi belum menyeluruh pelaksanaannya. Pada dasarnya budaya sekolah dimana saya bertugas baik, hanya saja tidak bisa membentuk karakter personality dari seseorang, dalam sekolah kebanyakan yang diajarkan hanya berupa teory yang kurang praktis.
Dan inilah sebuah kesalahan fatal yang telah membudaya hingga saat ini. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa keberadaan sekolah bukanlah hanya sebagai ladang bisnis semata atau hanya ladang mencari ilmu atau mencari nilai atau bahkan hanya tempat mencari ijazah. Tetapi, sekolah juga merupakan contoh sebuah masayarakat kecil dan sebagai tempat pembentukan mental para peserta didik yang kelak akan mengemban tugas bangsa ini.
6. LINGKUNGAN SEKOLAH
Potensi sumber daya manusia merupakan aset nasional sekaligus sebagai modal dasar pembangunan bangsa. Potensi ini hanya dapat digali dan dikembangkan serta dipupuk secara efektif melalui strategi pendidikan dan pembelajaran yang terarah, terpadu, yang dikelola secara serasi dan seimbang dengan memperhatikan pengembangan potensi peserta didik secara utuh dan optimal.
Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas harus didukung dengan lingkungan dan sarana yang sesuai untuk aktivitasnya. Hubungan antara kondisi lingkungan sekolah dengan sikap perilaku untuk anak sekolah dalam proses belajar mengajar belum diperhatikan.
Lingkungan merupakan tempat tinggal komunitas tertentu. Sebagai tempat tinggal, lingkungan akan dirawat oleh yang bertempat tinggal sesuai dengan karakternya masing-masing. Oleh karena itu dengan nyata kita dapat membedakan antara lingkungan perumahan elite, lingkungan kampung, lingkungan nelayan, lingkungan rumah kolong, dll. Selain dikarenakan oleh penghuni, lingkungan juga dapat diwarnai oleh fungsi, misalnya prabrik kimia, rumah sakit, apotik, dll. Namun demikian walau fungsi lingkungan sama, tetapi karakteristik penghuni berbeda akan mempengaruhi pula penataan lingkungan. Dari lingkungan kita dapat meneropong karakter / tabiat penghuninya.
Lingkungan sekolah merupakan indikator karakter civitas sekolah maupun kualitas sekolah secara keseluruhan. Sekolah merupakan lingkungan yang dialami oleh anak setiap hari. Lingkungan ini merupakan produk perancangan arsitektur yang dibuat oleh orang dewasa untuk anak. Dalam rangka mendukung pendekatan perancangan yang berorientasi pada kebutuhan pemakai (user-oriented), penelitian ini bermaksud mengungkapkan persepsi anak terhadap lingkungan sekolah melalui analisis gambaran visual tentang lingkungan sekolah yang selama ini dialaminya dan lingkungan sekolah yang diinginkannya. Hasil penelitian ini menunjukkan beragam cara pandang yang digambarkan oleh anak, yang dapat menjadi masukan berharga bagi proses perancangan lingkungan yang berorientasi pada kebutuhan anak.
Kita harus dapat membuat suasana pertama orang masuk sekolah kita terpukau oleh keindahan halaman depan sekolah. Indah tidak harus mahal, yang penting bersih tertata dan dirawat. Banyak sekolah yang tidak mengurus papan nama, misalnya: huruf rusak, tertutup tanaman, cat pudar, dll.
Banyak sekolah yang membiarkan halaman depan sekolah kosong tidak ada tanaman perindang, tidak ditata dan tidak dirawat.
Lingkungan lain yang harus ditata adalah ruang kelas. Ruang kelas merupakan tempat belajar mengajar. Agar proses belajar mengajar berjalan optimal ruangan harus ditata sedemikian rupa sehingga enak untuk belajar. Berilah gambar atau tanaman yang cocok sehingga membuat suasana menjadi meng-enakkan.
Banyak sekolah yang tidak memperhatikan ruang kelas. Loker dijadikan bak sampah. Meja kursi dibiarkan berantakan setelah ditinggal siswa.
Sepertihalnya ruang kelas, laboratorium juga merupakan tempat transfer knowledge. Suasana Laboratorium identik dengan kekotoran dan kekacauan. Alat dan bahan harus ditata yang rapi. Kalau perlu diberikan hiasan gambar atau tanaman yang sesuai.
Masih ada lingkungan lain diluar kelas dan Lab yang harus ditata, yaitu selasar sekolah dan halaman dalam sekolah. Selasar sekolah dan halaman dalam sekolah biasanya dipergunakan oleh siswa-siswa untuk beristirahat. Karena tidak memperhatikan kebersihan, maka biasanya selasar juga akan kelihatan kumuh. Banyak kertas bekas berserakan, bungkus jajanan tidak dibuang pada tempatnya, dan kondisi lainnya yang lebih buruk lagi.
Menjaga kebersihan merupakan “value” yang harus ditransfer kepada anak didik. Dan kuncinya, apabila pekerjaan kebersihan dilaksanakan secara berkala dan rutin maka tidak akan memberatkan. Misalnya anak diminta membuang sampah ditempatnya. Ada petugas kebersihan yang diatur jadwalnya. Penataan taman dilakukan bersama-sama secara gotong royong sehingga dalam suasana yang menyenangkan, dll.
Beberapa aksi lingkungan yang dapat dilakukan siswa dalam konsep sekolah berbudaya lingkungan antara lain:
a. kegiatan penghijauan
b. bakti sosial lingkungan
c. jalan sehat
d. kerja bakti lingkungan
e. melakukan konservasi lahan dengan penanaman
f. pemeliharaan tanaman
g. pemanfaatan kebun bibit
h. Penambahan koleksi kebun sekolah untuk proses pembelajaran keanekaragaman hayati
i. Perbanyakan tanaman untuk melatih life skill
j. Konservasi flora & fauna
k. pengenalan konsep konservasi
l. implementasi PLH
m. melaksanakan ”Gugur Gunung” atau bedol sekolah
n. monitoring dan evaluasi.
o. penilaian antar kelas.
p. lomba barang bekas
q. mengembangkan produk olahan bahan sekitar
r. mengadakan pameran produk kreasi siswa
Pendidikan mengenai lingkungan sangat penting. Namun pendidikan ini harus memperoleh dukungan lebih dari berbagai unsur yang ada dalam lingkungan sekolah.
Komponen pendidikan yang tidak kalah pentingnya adalah sarana dan prasarana yang mendukung. Mulai dari bangunan fisik, ruang kelas, taman, perpustakaan, laboratorium, sarana olah raga dan kesenian, arena bermain, kantin, perlengkapan kelas, sampai dengan alat peraga edukasi yang dimiliki. Seiring dengan kemajuan bidang informasi dan teknologi, nampaknya bukan hal yang baru sebuah sekolah memiliki fasilitas akses jaringan internet dan website sendiri, dimana setiap stake holders dapat berinteraksi dan berkomunikasi di dunia maya.
Hal ini, akan sangat membantu bagi orang tua untuk memantau perkembangan putra-putrinya secara cepat tanpa harus secara fisik datang kesekolah. Dengan didukung sarana dan prasarana yang baik, diharapkan semua peserta didik dapat belajar secara enjoy, nyaman, dan betah. Sekolah diibaratkan sebagai rumah kedua bagi anak-anak, sehingga sekolah yang baik mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan siswa. Hal yang perlu diperhatikan juga mengenai rasio jumlah siswa dengan luas ruangan kelas serta fasilitas pembelajaran yang lain.
Lokasi sekolah dan lingkungan
Lokasi yang dimaksud dapat dipandang dari jarak sekolah ke rumah, lingkungan sekitar dan sarana transportasinya. Bisa dibayangkan seorang anak harus bangun pagi-pagi sekali karena letak sekolahnya jauh. Tentu ia pulang dalam keadaan lelah karena jarak yang ditempuhnya memakan waktu yang lama. Belum lagi jika terjadi kemacetan lalu lintas, bisa dimungkinkan sering terlambat pulang maupun masuk sekolahnya.
Lalu kapan ia bisa belajar di rumah dengan nyaman? Bagaimana ia bisa mengembangkan interaksi dengan anggota keluarga lain di rumahnya? Maka, faktor lokasi dan lingkungan ini hendaknya diperhatikan oleh orang tua dan anak itu sendiri dalam menentukan sekolah pilihannya. Perlu dipikirkan juga mengenai sekolah yang berlokasi di pusat perkotaan atau keramaian dan yang berada di pinggiran atau lebih dekat dengan suasana alam, semua memiliki plus-minus-nya.
7. STRATEGI PERUBAHAN BUDAYA DAN IKLIM SEKOLAH
KONSEP Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) ditengarai banyak pihak sebagai cara mutakhir peningkatan mutu pendidikan di Tanah Air. MBS pada dasarnya merupakan pendelegasian otoritas pengambilan keputusan untuk mengelola sumber daya keuangan, kurikulum, serta profesionalisme guru ke tingkat sekolah. Artinya, segala keputusan yang menyangkut pengelolaan sekolah sedapat mungkin diputuskan oleh pihak terkait dalam lingkungan sekolah, seperti kepala sekolah, guru, orang tua murid, dan tokoh masyarakat setempat yang tergabung dalam dewan sekolah.
Menurut Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, MBS sedang dan telah diujicobakan di 1.000 sekolah. Dari beberapa laporan awal diketahui bahwa dalam penerapannya ternyata konsep ini masih belum menunjukkan hasil yang sepenuhnya memuaskan.
Di satu pihak, sejumlah sekolah yang menerapkan MBS telah mampu mewujudkan proses belajar yang aktif, efektif, dan menyenangkan. MBS berhasil menggalang partisipasi aktif masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan dan transparansi manajemen sekolah.
Di pihak lain, MBS masih belum menyentuh perubahan mendasar dalam meningkatkan sistem `pengelolaan pendidikan partisipatif`. Penyebabnya, antara lain, karena lemahnya kepemimpinan kepala sekolah, kurang profesionalnya guru, serta sikap apatis masyarakat.
Dari perspektif sosiologis, kegagalan penerapan MBS bermuara dari tidak adanya perubahan budaya sekolah (school culture), yakni berubahnya semangat, sikap, dan perilaku pihak-pihak yang terkait dengan sekolah. Karenanya, penerapan MBS mensyaratkan tidak hanya perubahan kebijakan legal dan formal, melainkan pula perubahan nilai, semangat, sikap, dan perilaku para aktor sekolah seperti kepala sekolah, guru, orang tua murid, dan siswa.
Penerapan MBS memerlukan perubahan budaya sekolah dari budaya konservatif yang pasif dan sentralistik menjadi budaya inovatif yang egaliter, aktif, dan dinamis. Budaya sekolah Menurut Deal dan Peterson (1999), budaya sekolah adalah sekumpulan nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol yang dipraktikkan oleh kepala sekolah, guru, petugas administrasi, siswa, dan masyarakat sekitar sekolah.
Budaya sekolah merupakan ciri khas, karakter, dan citra sekolah tersebut di masyarakat luas. Untuk mengenali budaya sekolah, cobalah masuk ke sekolah favorit dan sekolah yang mutunya kurang baik (negeri atau swasta).
Perhatikan bagaimana proses belajar-mengajar, disiplin, dan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah tersebut. Kemudian, bandingkan situasi dan kondisi antara dua sekolah tadi. Niscaya akan dirasakan suasana, iklim dan kebiasaan yang sangat berbeda. Suasana, iklim, dan kebiasaan itulah yang dinamakan budaya sekolah.
Menurut Sergiovanni (1999), budaya sekolah memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap suatu proses perubahan berencana (planned change). Karenanya, dalam konteks penerapan MBS, Sergiovanni menyarankan agar para pengambil kebijakan, para penilik, dan kepala sekolah menggunakan pendekatan budaya sekolah atau school culture approach.
Alasannya:
Pertama, pendekatan budaya lebih menitikberatkan faktor manusia di atas faktor-faktor lainnya.
Kedua, pendekatan budaya menekankan pentingnya peran nilai dan keyakinan dalam diri manusia.
Ketiga, pendekatan budaya memberikan penghormatan dan penerimaan terhadap perbedaan-perbedaan yang ada.
Strategi perubahan
Strategi perubahan budaya sekolah, kata Deal dan Kennedy (1985), meniscayakan perubahan dalam tiga tataran: yaitu tataran nilai yang dianut, tataran praktik keseharian, dan tataran simbol-simbol budaya.
Dalam tataran nilai, perubahan yang harus dilakukan adalah mengubah nilai-nilai lama yang menghambat dengan nilai baru yang mendukung MBS. Nilai lama yang bercirikan nilai sedang-sedang saja (mediocre values), seperti berpuas diri, tertutup, pasif, dan ketergantungan, harus diubah menjadi nilai baru yang bercirikan nilai keunggulan (excellent values), seperti terbuka terhadap innovasi, kompetitif, berinisiatif, independen, dan bertanggung jawab.
Dalam tataran praktek keseharian, transformasi yang harus dilakukan adalah mengubah sikap dan perilaku lama yang bercirikan `asal-asalan` (asal mengajar, asal datang, dan asal jadi), menjadi sikap dan perilaku baru yang bercirikan kesungguhan dan dedikasi.
Perilaku lama yang cenderung menunggu petunjuk dan berorientasi ke atasan juga direformasi menjadi perilaku baru yang penuh inisiatif dan berorientasi kepada proses belajar siswa.
Perubahan ini dapat diwujudkan melalui tiga hal: Pertama, pensosialisasian visi dan misi sekolah sebagai tujuan ideal yang ingin dicapai pada masa mendatang. Kedua, penetapan rencana strategis mingguan atau bulanan sebagai tahapan dan langkah sistematis yang akan dilakukan oleh semua pihak di sekolah. Ketiga, pemberian penghargaan terhadap prestasi guru dan siswa sebagai usaha pembiasaan (habit formation) yang menjunjung sikap dan perilaku yang profesional. Penghargaan dapat berwujud materi maupun nonmateri, seperti ucapan selamat atas prestasi tertentu.
Dalam tataran simbol-simbol budaya, perubahan yang harus dilakukan adalah mengganti simbol budaya yang konservatif dan sentralistik dengan simbol budaya yang dinamis.
Perubahan simbol dapat dilakukan dengan mengubah penataan kelas dan ruang guru, serta pemasangan hasil karya siswa, foto-foto, dan moto.
Misalnya, penataan tempat duduk siswa yang berpusat pada guru harus diubah menjadi tempat duduk yang mendorong interaksi antarsiswa sehingga mereka dapat belajar dengan aktif, kreatif, dan menyenangkan. Hasil karya siswa yang berupa gambar, karangan, puisi, dan kerajinan harus dipasang di ruangan kelas untuk mendorong kebanggaan berprestasi. Foto-foto ilmuwan serta karya-karyanya perlu juga perlu dipajang guna merangsang motivasi belajar siswa.
Sangat perlu.
Adalah kurang tepat, untuk tidak mengatakan naif, jika penerapan MBS hanya dilakukan dengan mengubah struktur organisasi atau membentuk dewan sekolah. Pendekatan budaya sekolah sangat diperlukan dalam penerapan MBS. Pelaksanaan MBS meniscayakan proses perubahan pada nilai, semangat, sikap, dan perilaku semua komponen sekolah.
Sejauh ini strategi perubahan budaya dan iklim sekolah di tempat saya bertugas, tidak mengalami perkembangan yang signifikan, dimana adanya program pemerintah tentang MBS, belum direspon secara menyeluruh, dalam arti hanya faktor-faktor tertentu saja yang sudah diterapkan, tapi belum menyeluruh pelaksanaannya.
8. PERILAKU KELAS DIDIK MENERIMA PEMBELAJARAN SEMESTER INI
Saya mengamati dengan seksama siswa-siswi di kelas dan mencatat dengan detail 4 gejala-gejala perilaku yang khusus.
1. Ciri perilaku Pembosan
2. Ciri perilaku Pemalu
3. Ciri perilaku Penakut
4. Ciri perilaku Bersemangat
5. Ciri perilaku Penyendiri
Cara yang saya gunakan merupakan cara yang klasik dan tiap hari dilakukan entah berapa tahun berjalan. Cara itu biasanya tanya jawab, langsung perintah buka buku, langsung menerangkan, dan langsung menyuruh siswa. Cara lain tidak pernah dilakukan.
Tapi saya juga melakukan variasi agar siswa senang dalam belajar. Berikut ini metode mengajar yang saya pakai untuk menambah cara mengajar yang lama.
Berangkat dari Siswa
Memulai pelajaran dari diri siswa. Mengamati dengan cepat siswa yang hadir kemudian memulai dari siswa yang diamati tersebut.
Contoh, jika saya akan membahas pemilu, berangkat dari siswa yang halaman rumahnya digunakan untuk pilkada. Begitu pula, kalau saya akan mengajar tentang mencangkok, berangkat dari bentuk cangkok dari rumah atau halaman rumah siswa.
Berangkat dari Isu Nasional
Isu nasional datang bertubi-tubi tanpa henti. Banyak isu yang menarik untuk dijadikan bahan memulai pembelajaran. Saya memulai dari isu nasional kemudian masuk ke inti pelajaran.
Berangkat dari Kejadian
Kejadian yang telah lalu, yang dialami siswa atau saya sendiri dapat digunakan untuk memulai pelajaran. Saya memulai bercerita tentang pengalaman yang baru saja saya alami.
Contoh, untuk masuk ke topik mengukur bidang datar, saya dapat memulai dengan pengalaman bermain voley.
Berangkat dari Gambar
Saya membawa gambar beraneka bentuk, besar-besar ukurannya, atau kecil-kecil. Gambar itu dipakai untuk memulai pelajaran dengan menarik.
Berangkat dari Teka-Teki
Banyak teka-teki yang menarik untuk digunakan memulai pelajaran. Dari teka-teki, siswa langsung mengolah pikiran yang berkaitan dengan topik.
Berangkat dari Benda Sekitar
Saya membawa benda sekitar untuk memulai mengajar, yakni batu, kerikil, tanaman, daun, akar, dan sebagainya. Siswa saya ajak untuk mengidentifikasi benda sekitar itu sebelum ke pembahasan inti.
Berangkat dari Film dan Siaran Radio
Saat memulai pelajaran, saya ajak anak menonton film singkat atau rekaman siaran radio. Kemudian, saya memancing pertanyaan dari isi film atau radio. Kemudian memulai dengan pelajaran initinya.
Masih banyak lagi cara memulai pelajaran yang lebih menyenangkan. Misalnya melalui baca puisi, cerita singkat/dongeng, lagu, gerakan tubuh, boneka, yel-yel, dan yang lainnya. Saya tidak menutup diri dalam memulai mengajar hanya dengan tanya jawab.
Sekolah adalah tempat belajar bagi siswa. Maka tugas saya sebagai guru di kelas adalah "membantu siswa belajar", dengan mengatur Proses Belajar - Mengajar serta menyediakan kondisi belajar yang optimal. Saya tidak hanya seorang pengajar, tetapi juga seorang manajer kelas. Di kelas ada dua kegiatan yang memang berhubungan erat satu sama lain, namun dapat dan harus dibedakan karena tujuan dan sifat- sifatnya memang berlainan
Dalam kelas dapat muncul masalah pengajaran atau masalah pengelolaan. Karena itu setiap masalah yang timbul di kelas perlu ditanggulangi sesuai dengan sifat masalahnya. Masalah pengelolaan kelas terjadi bila ada kesenjangan antara tingkat keterlibatan siswa yang seharusnya dalam proses belajar - mengajar dengan keterlibatan yang nyata- nyata terjadi.
Kesenjangan ini dapat terjadi karena berbagai sebab, yaitu orang (siswa, guru), sarana (misalnya media pengajaran dan fasilitas fisik) dan organisasi (misalnya: perubahan jadwal, pergantian guru, dsb.).



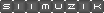






















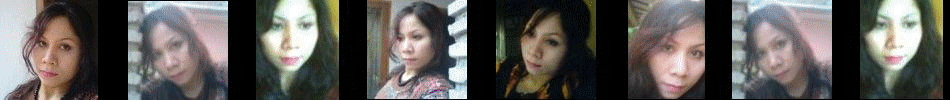






Tidak ada komentar:
Posting Komentar